Beyond the Scientific Way
Belajar Menjadi Guru, Dosen, Widyaiswara, Ustadz …
Friday, January 4th, 2013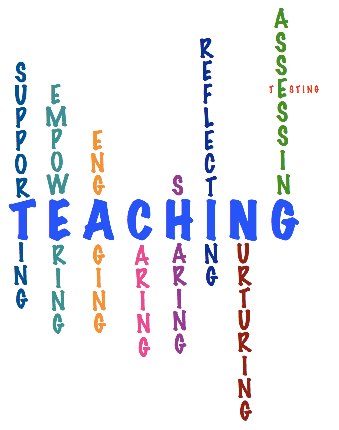 Siapakah guru dalam hidup Anda yang paling Anda kagumi?
Siapakah guru dalam hidup Anda yang paling Anda kagumi?
Apa yang sangat menginspirasi dari guru Anda itu?
Guru adalah salah satu profesi yang paling dikenal anak-anak. Sangat banyak anak punya cita-cita jadi guru, selain mungkin jadi dokter, insinyur atau pilot. Tetapi ketika mereka semakin besar, semakin kenal dengan kenyataan kehidupan guru, semakin sedikit yang masih mempertahankan cita-cita ini. Baru akhir-akhir ini saja, profesi guru “booming” lagi. Itu setelah di berbagai daerah, guru mendapat tunjangan profesi 1x gaji. Akibatnya, FKIP di berbagai kampus menjadi favorit, bahkan di beberapa kampus, persaingannya mengalahkan FT atau FE.
Sejujurnya, saya termasuk yang tidak pernah punya cita-cita jadi guru. Kalau jadi ilmuwan ya. Tetapi ternyata perjalanan hidup saya menyebabkan saya melewati fase menjadi guru, juga dosen, widyaiswara, dan bahkan ustadz 🙂 Walaupun semua mungkin pakai embel-embel “Luar Biasa”.
Saya pertama kali “pura-pura” jadi guru, itu kelas 2 SMP, ketika di sekolah, guru sejarah saya mencoba menerapkan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Anak-anak diminta membentuk kelompok @ 4 orang, lalu masing-masing diberi tugas suatu bab di buku paket, lalu “mengajar” siswa yang lain di depan kelas, bahkan sampai memberikan test. Tetapi seingat saya tidak semua kelompok sempat maju, karena waktu keburu habis. Saya beruntung termasuk yang sempat tampil, bahkan saya yang didaulat untuk yang berdiri mengajar di depan kelas.
Setelah itu ternyata saya jadi sering “mengajar” untuk berbagai hal yang lain. Mengajar PKS (Patroli Keamanan Sekolah), lebih tepatnya mungkin disebut Melatih. Sebelumnya saya dan beberapa kawan dilatih menjadi anggota PKS oleh Polres. Tugas PKS itu yang terpenting seperti Polantas, tetapi khusus untuk menyeberangkan anak-anak sekolah di depan sekolah. Maklum tenaga polisi saat itu dirasa terbatas. Setelah itu, beberapa kali seminggu, pagi pukul 6.30 kami sudah bertugas. Setelah praktek beberapa bulan, sekolah merasa perlu regenerasi, sehingga kami melatih adik-adik kelas.
Setelah PKS, pengalaman menjadi “guru” yang lebih panjang ada di Pramuka dan KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) di SMA. Walaupun kalau direnung-renungkan sekarang, banyak “pelajaran” di Pramuka saat itu yang “nggak mutu”, tapi dulu koq ya percaya diri saja ya … he he … Kalau KIR agak mending. Sampai sekarangpun saya kira masih banyak pelajaran yang relevan, bahkan tidak cuma untuk siswa SMA, bahkan untuk sarjana yang lagi meniti karier jadi peneliti muda 🙂
Sewaktu saya kuliah di Austria, saya juga punya pengalaman beberapa kali jadi “guru”. Pertama “guru” internet. Ini terjadi tahun 1995, sewaktu penggunaan internet masih relatif awal. Mungkin ini lebih tepat disebut “tutorial”. Kedua tahun 1996, “guru” bahasa Indonesia untuk orang asing. Ternyata rumit juga mengajar bahasa Indonesia yang sistematis untuk orang bule. Murid-murid saya saat itu ada 3 kelompok motivasi. Pertama yang motivasinya pekerjaan, yakni mereka akan dikirim bekerja di Indonesia (biasanya teknisi atau personil bisnis pariwisata). Kedua yang motivasinya travelling. Ada murid saya yang profesinya Profesor Fisika, tetapi hobby travelling, dan liburan mendatang ingin “blusukan” mengelilingi Indonesia. Alamak, waktu itu saya juga belum pernah keliling Indonesia. Yang lucu yang ketiga, motivasinya keluarga. Ada murid saya, wanita Austria yang akan menikahi pria Indonesia. Jadi dia perlu belajar banyak hal agar keluarganya harmonis.
Tahun 1997, sepulang dari Luar Negeri, beberapa saat lamanya saya diminta mengajar di sebuah kursus programming di suatu perusahaan. Mereka minta diajar programming dalam Visual Basic. Sejujurnya, saat saya meng-iyakan, saya belum pernah lihat Visual Basic. Saya memang punya pengalaman programming yang cukup panjang dalam C, Pascal, Fortran, Lisp, SQL dan Basic. Tetapi Visual Basic? Akhirnya saya praktis hanya menang 1 minggu dari peserta. Tetapi alhamdulillah dalam waktu singkat saya sudah lumayan expert. Repotnya ketika di akhir kursus, ada peserta yang tanya, apakah saya sudah punya “Microsoft Certified Programmer” ? Saya menjawab diplomatis, “Sepertinya Bill Gates juga belum punya tuh? ” 🙂
Karena saya sudah mengantongi gelar Doktor, maka mulailah saya beranjak dari “guru kursus” ke dosen. Ada prodi S1 suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meminta saya masuk dalam tim dosennya. Teorinya, kalau saya masuk, ijazah S3 dan sejumlah publikasi saya bisa mendongkrak nilai akreditasi BAN-PT untuk prodi di PTS tersebut. Ternyata betul. Bahkan waktu itu, prodi di PTS tersebut terakreditasi lebih dulu dari PTN pembinanya !!! Tetapi setelah terakreditasi, tiba-tiba jumlah mahasiswa yang diterima PTS itu berlipat 3x. Dosennya yang kewalahan. Kalau cuma mengajar sih mungkin tidak terlalu berat. Tetapi kalau harus mengoreksi tugas, wow … capek dech … Apalagi mengajar di LCU (Low Cost University) ini harus lebih banyak ibadahnya … 🙂 Lima tahun kemudian, karena saya semakin sibuk di kantor, saya makin mengurangi jam mengajar saya di PTS tersebut, sampai akhirnya off sama sekali.
Saat itu saya juga mencoba menjadi dosen program S2 di IPB dan di UPM (Universitas Paramadina Mulya). Yang S2 di IPB ini program internasional, wajib pakai bahasa Inggris. Sedang yang di UPM kelas eksekutif, jadi kuliahnya malam. Sangat berbeda dengan S1, menjadi dosen S2 jauh lebih “santai”. Mahasiswanya tidak banyak, tetapi honornya banyak … he he … Kadang saya berpikir, jangan-jangan honor saya ngajar S2 ini sebenarnya untuk jerih payah ngajar S1 di LCU itu … 🙂 Yang jelas, ndosen di S2 bersama para eksekutif itu membuat kita jadi terus terasah. Kita mengakumulasi berbagai pengalaman dan wawasan.
Meski menjadi selingan yang menggairahkan, tetapi karena saya secara resmi bukan dosen, maka kadang-kadang tugas ini sedikit “terganggu”. Yang paling ringan adalah ketika tiba-tiba ada jadwal rapat yang berdekatan dengan jadwal mengajar. Kadang-kadang sulit kita mencari waktu pengganti. Yang lebih repot lagi adalah ketika kita punya atasan yang kurang suka atau bahkan tidak setuju kita “ndosen” pada jam kerja. Dianggapnya itu buang-buang waktu, atau bahkan “korupsi waktu”. Padahal sesungguhnya, pada saat mengajar, kita juga bertambah ilmu, dan juga memperluas jejaring, yang juga memiliki multiplier effect pada tugas-tugas kita di kantor. Mahasiswa S2 itu berasal dari berbagai daerah, berbagai lembaga, juga berbagai profesi dan latar belakang.
Ada beberapa kampus yang secara tersirat menawari saya pindah, jadi dosen full-time saja di sana. Mereka mengatakan, kalau jadi dosen full-time nanti bisa jadi Professor. Waktu itu saya coba hitung-hitung angka kredit kumulatif saya kalau dihitung sebagai dosen. Ternyata jauuuh. Terutama karena saya tidak bisa memenuhi porsi tri-darma perguruan tinggi yang pertama yaitu pendidikan/pengajaran. Ya maklum, ngajar di sana-sini cuma 2 SKS. Paling total cuma 6 SKS per semester … Kalau mau “ngebut”, mesti menulis buku ajar. Sebenarnya menulis buku ajar tidak terlalu susah, karena tidak harus penemuan sendiri. Bisa menggubah ulang apa yang pernah ditulis orang lain. Tetapi sepertinya saya nggak bisa menuliskan sesuatu yang tidak pernah saya dalami sendiri. Untunglah, kemudian muncul SKB Mendiknas-Kepala LIPI-Menpan yang mengesahkan adanya Profesor Riset, yakni jenjang Professor yang menjadikan riset sebagai komponen utama.
Selain itu, untuk berbagai diklat dari berbagai kementerian/lembaga saya juga diminta menjadi “Widyaiswara Luar Biasa”. Widyaiswara agak berbeda dengan dosen, karena yang dididik bukan mahasiswa (apalagi mahasiswa S1), tetapi orang dewasa yang kadang merasa sudah lebih berpengalaman, atau bahkan merasa “untuk apa harus ikut diklat lagi, toh sudah tua dan sebentar lagi pensiun”. Jadi perlu pendekatan yang berbeda, bahasa kerennya “Andragogi”, bukan “Pedagogi”. Di diklat yang diadakan Bakosurtanal/BIG, saya kadang menjadi WLB untuk bidang Pemetaan, Penegasan Batas, Penataan Ruang, Penanggulangan Bencana dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Di LIPI saya menjadi WLB Diklat Fungsional Peneliti tingkat Lanjut. Jadi WLB ini tidak terlalu stress, karena kita cukup banyak cerita dari pengalaman kita saja, dan gak usah bikin soal yang rumit seperti ujian mahasiswa. Biasanya sih – asal tidak keterlaluan – semua peserta diklat akan lulus. Toh terserah mereka, apakah ilmu yang kita berikan akan terpakai atau tidak pada lingkup pekerjaan mereka.
Yang terakhir setelah guru – dosen – widyaiswara, itu adalah ustadz. Ini seharusnya pos yang paling tinggi. Di Mesir itu, lulusan S1 syari’ah tidak langsung dipanggil Ustadz, tetapi “Mu’id”. Nanti kalau sudah S2, dia akan dipanggil “Musaid Mudaris”. Setelah S3 dipanggil “Mudaris”. Setelah mengajar dan riset kira-kira 5 tahun, akan dipanggil “Musaid Ustadz”. Baru setelah 10 tahun sejak S3, kalau angka kumnya tercapai dan senat setuju, akan dipanggil “Ustadz”. Jadi rupanya Ustadz itu sama dengan Professor. Tetapi di Indonesia, panggilan Ustadz bisa dicapai siapa saja. Sangat egaliter. Dan tahukah Anda, bahkan sejak saya masih SMP, saya sudah dipanggil “Ustadz” !!! Itu terjadi lantaran saya membantu mengajar membaca al-Qur’an belasan anak-anak kecil di masjid kampung. Kemudian menggantikan ayah saya yang wafat mengisi majlis taklim Ibu-ibu. Kemudian mengisi khutbah di sekolah. Tentu saja, sebagai “Ustadz” tingkah laku kita lalu juga jadi sorotan. Tapi ini bagi saya tidak masalah. Ketika saya pada usia 26 tahun sudah naik haji, tambah disorot lagi !!! Karena banyak orang yang menunda naik haji, karena takut nggak bisa “membuat dosa” lagi … Itu tanda orang yang kurang cerdas. Karena, kata Imam Ghazali, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati, dan kematian bisa datang kapan saja, tidak nunggu tua. Karena itu, ayo buruan jadi “Ustadz” — mumpung di Indonesia belum perlu syarat macam-macam seperti di Mesir – asal tahu diri saja kapasitas ilmunya … 🙂
Tapi fenomena “Ustadz TV” atau “Ustadz Google” akhir-akhir ini memang agak memprihatinkan. Seorang dianggap ustadz hanya oleh aktivitas ceramahnya, dan bahannyapun “cuma disedot dari Google”. Padahal aktivitas Ustadz – dan juga guru/dosen/widyaiswara pada umumnya – yang hakiki itu adalah MENGUBAH (CHANGE). Mengubah dari mindset (pola pikir), kemudian behaviour (perilaku), dari yang kurang cerdas menjadi cerdas, dari yang kurang cekatan menjadi cekatan, dan dari yang kurang islami menjadi islami – sesuai syari’ah. Percuma saja ngustadz di TV, ditonton jutaan orang, kalau tidak satupun yang berubah, karena isinya cuma banyolan. Lebih gawat lagi, kalau isinya memang mengubah, tetapi malah mengubah jadi makin tidak islami. Karena orang yang tersesatkan akan berkilah, “Lho ini kata Ustadz Fulan di TV hukumnya halal koq”. Padahal “fatwa halal” Ustadz Fulan itu ternyata cuma pakai “dalil perasaan”, kalau tidak “katanya” ya “pokoknya”.
Baik guru, dosen, widyaiswara maupun ustadz, semua memiliki tanggungjawab sampai akherat sana. Karena itu beruntunglah mereka yang memposisikan semua amal itu untuk ibadah, bukan sekedar untuk mencari penghidupan. Kita tidak usah risau dengan kompensasi yang kadang tidak sesuai dengan jerih payah, karena “Gusti Allah ora sare” (Tuhan tidak pernah tidur). Dia Yang Maha Adil tidak akan pernah membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Hal Jazaa’ul Ihsani Illal Ihsan”.
Salam.
Faktor-Faktor Yang Memperlemah Ulama
Sunday, April 1st, 2007Oleh: Dr. Fahmi Amhar (Dosen Pascasarjana Universitas Paramadina)
Berapa banyak ulama yang kita miliki? Ini pertanyaan sederhana, namun sulit dijawab; meski kita hanya mencari tahu secara kuantitatif, belum secara kualitatif. Kalau pertanyaannya dimodifikasi menjadi: Berapa alumni pondok pesantren di Indonesia? Jawabannya lebih mudah. Hitung saja pesantren yang terdaftar di Departemen Agama. Tentu kapasitas pesantren tidak merata. Yang bisa dihitung adalah yang sudah menerapkan administrasi modern. Padahal banyak pesantren kita yang tradisional, tidak mengenal pendaftaran maupun ujian dengan standar tertentu. Jika diasumsikan hanya ada 2000 pesantren se-Indonesia (5 buah per Kabupaten), dan rata-rata 100 lulusan pertahun, dapatkah diharapkan lahir 200.000 “ustadz”? Berapa dari mereka yang menjadi ulama?
Sulit dijawab. Berbeda dengan sarjana, doktor atau profesor yang definisinya jelas. Ulama—yang sejatinya adalah “scholar”—jauh lebih sulit. Tidak setiap ustadz atau dai pantas disebut ulama. Bahkan yang di MUI pun tidak semua merasa nyaman disebut ulama.
Ulama dalam “Jebakan”
Kini ulama adalah mahluk langka. Jarang anak kecil yang bercita-cita mau menjadi ulama. Orangtua pun kalau mengirim anaknya ke pesantren hanya agar anaknya menjadi salih, bukan menjadi ulama.
Di sisi lain, kalau kita memperkenalkan tokoh Indonesia ke orang Timur Tengah bahwa dia seorang ulama, orang Timur Tengah akan balik bertanya: Ulama di bidang apa? Apakah dalam ulumul Quran? Hadis? Fikih? Tarikh? Kalau kita tidak menjelaskan, mereka akan ragu, “Ulama apa itu? Ahli al-Quran bukan; ahli hadis bukan; ahli fikih bukan; ahli tarikh bukan. Jadi, ahli apa?”
Walhasil, kita tahu bahwa ulama saat ini sangat langka. Dari yang langka ini, lebih banyak ulama yang lemah daripada yang kuat. Yang lemah ini tidak menjadi inspirasi bagi umat, tidak memimpin umat keluar dari keterpurukannya, bahkan mereka tidak jarang justru menjadi bagian dari sistem yang menindas umat.
Apa sesungguhnya faktor-faktor yang membuat ulama yang langka ini semakin lemah? Secara umum ada tiga ”jebakan” bagi ulama. Pertama: jebakan pemikiran yang terjadi pada dirinya sendiri. Kedua: jebakan kultural yang “disiapkan” masyarakat. Ketiga: jebakan sistem yang direkayasa oleh para penguasa.
Agar dapat keluar dari jebakan ini, para ulama wajib memiliki kesadaran ideologis, di mana posisinya saat ini, agar dia tidak terjebak di salah satu atau ketiganya.
1. Jebakan Pemikiran.
Jebakan pemikiran adalah jebakan yang paling lembut sehingga yang terjebak tidak merasa dirinya terjebak. Jebakan pemikiran ini ada tiga macam. Pertama: sekularisasi. Sekularisasi adalah pemisahan agama dari kehidupan publik, yakni kehidupan tempat interaksi tak terbatas seluruh warga, baik Muslim maupun bukan, dalam segala aspek kehidupan: politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dll.
Pahit untuk mengakui, bahwa sebagian besar ulama kita sudah tersekularisasi di segala sisi. Mereka canggung berbicara masalah publik dari sisi Islam. Mereka membatasi diri untuk berbicara hanya saat ada persoalan moral seperti pornografi, miras, perjudian, pelacuran. Kalaupun mereka berbicara tentang terorisme, itu karena terorisme dikaitkan dengan ustad dan pesantren. Mereka juga hanya peka terhadap gerakan sesat (Ahmadiyah, shalat dwibahasa, dsb). Sebaliknya, mereka canggung untuk duduk bersama membahas pengaturan sumberdaya alam menurut Islam atau mengatasi krisis pangan menurut Islam; seakan-akan dalam masalah-masalah ini, Islam tidak mempunyai solusi.
Kalau berbicara tentang pendidikan Islam, yang terlintas hanya mata pelajaran agama di sekolah, atau pendidikan oleh yayasan Islam (termasuk pesantren). Jarang yang berpikir bahwa pendidikan Islam itu menyangkut segala segi, dari muatan kurikulumnya yang harus mengacu pada akidah Islam di segala pelajaran (termasuk bahasa, matematika, IPA, IPS) hingga bagaimana pendidikan itu bisa dibiayai sehingga semua warga bisa mendapatkan akses pendidikan bermutu yang terjangkau.
Kedua: dakwah ishlâhiyah dan khayriyah. Sejak sekularisasi menjadi arus utama, Islam dipelajari hanya sebatas ajaran perbaikan individu atau keluarga. Dakwah akhirnya hanya terfokus pada perubahan individual yang bersifat kebajikan (khayriyah). Topik yang dominan adalah fikih praktis (ibadah, tatacara makan/berpakaian, nikah, muamalah sehari-hari dan akhlak). Dakwah sudah dianggap sukses jika berhasil menjadikan seseorang rajin shalat atau perempuan mau berbusana Muslimah. Terkait dengan aktivitas masyarakat, dakwah ditekankan pada kepedulian sosial seperti sedekah, menyantuni anak yatim hingga mendirikan sekolah dan rumah sakit. Bagaimana memberikan solusi tuntas dan mendasar terhadap segala masalah umat (ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, perundang-undangan, dll), hal itu jarang dijadikan target.
Ketiga: pemikiran “asketis”. Derap kehidupan hedonis, apalagi yang dibawa Kapitalisme, membuat sebagian ulama bereaksi dengan hidup bak pertapa sufi (asketis). Dakwah mereka fokus pada aspek ruhiah (spiritual) dan mengajak masyarakat menjauhi dunia. Walhasil, pada saat mendengar nasihat mereka, orang bisa mengucurkan air mata. Namun, begitu keluar majelis, aktivitas dunianya tidak mengacu syariah, karena syariah itu sendiri tidak pernah dibahas. Orang diasumsikan otomatis jadi baik ketika pikirannya mengingat Allah. Padahal faktanya, amal seseorang bergantung pada pemahaman syar‘i yang dimilikinya. Ada pemilik bank yang tiap hari bergelimang riba, namun dia tidak merasa berdosa, karena sudah rajin tahajud dan puasa sunnah.
2. Jebakan Kultural.
Jebakan kultural atau budaya terjadi di—dan dilakukan oleh—masyarakat. Masyarakat menggunakan pengalamannya dalam berinteraksi dengan agama lain saat memahami Islam. Jebakan kultural ini dapat memaksa seorang ulama yang semula kuat karena ikhlas menjadi lemah karena bias. Ada tiga jebakan kultural:
Pertama: mitos ulama. Pada semua ajaran lain, keyakinan berasal dari mitos atau aksioma yang tidak rasional. Ketika beralih ke Islam, penganut mitos pun memandang akidah Islam sebagai mitos. Rasul saw. berubah dari sosok manusia teladan menjadi sosok keramat yang supranatural. Bahkan ulama tiba-tiba dianggap “orang suci” yang mustahil salah, seperti penganut Katolik memandang Paus. Belakangan muncul orang-orang yang memanfaatkan hal ini demi keuntungan pribadi. Mereka melegitimasi diri di depan orang-orang awam dengan ayat al-Quran atau hadis yang diselewengkan. Lalu muncullah bid‘ah di mana-mana.
Di sisi lain, ulama dimitoskan dengan segala idealitas dalam pandangan awam, bukan pandangan syariah. Saat ulama itu melakukan hal yang dibenci awam (misalnya poligami), gelar “orang suci” tiba-tiba lenyap. Mereka tidak bisa menerima kenyataan, bahwa “ulama juga manusia”.
Kedua: mitos bahasa. Sebagai bahasa al-Quran, bahasa Arab adalah bahasa ilmu pengetahuan Islam. Namun, di masyarakat non-Arab, kini bahasa ini sudah menjadi “hak istimewa” selapis kecil ulama. Sekadar tulisan Arab saja kadang dianggap keramat dan mampu mengusir setan. Orang yang pintar membaca al-Quran langsung dipanggil ustadz. Yang fasih berbahasa Arab (baca kitab kuning) dijuluki ulama, tanpa melihat lagi pemahaman Islamnya.
Ketiga: mitos ijtihad. Pada zaman sekarang, ijtihad dimitoskan sama dengan berpendapat. Setiap orang akhirnya boleh berijtihad, sekalipun tanpa bekal memadai. Tidak aneh, muncullah fatwa-fatwa nyleneh. Namun, ini ditoleransi dengan dalil, bahwa ijtihad itu, kalau benar mendapat dua pahala, dan kalau salah mendapat satu pahala. Padahal yang terjadi kadang-kadang hanyalah adopsi terhadap paham sekular yang dilabeli Islam, yang jauh sekali dari kategori ijtihad.
3. Jebakan Sistem.
Para penguasa korup pada zaman manapun melihat para ulama sebagai orang-orang yang berpotensi menghalangi mereka. Karena itu, penguasa fâsid ini akan berupaya melemahkan para ulama, baik secara “legal” maupun “ilegal”. Yang legal ada tiga macam:
Pertama: depolitisasi. Ulama dimarjinalkan dari kancah politik dengan sekularisme. Ulama yang menolak sekularisme akan mundur dari arena; yang ada dalam sistem, mau tak mau, akan sama sekularnya. Contoh, pada masa lalu, ada UU yang mewajibkan asas tunggal bagi ormas dan parpol. Akibatnya, para ulama praktis kehilangan ‘rumah’, kecuali yang mau pindah ke ormas atau parpol pendukung penguasa. Meski berdalih akan “mengislamkan dari dalam”, yang terjadi justru sebaliknya.
Kedua: pragmatisme. Ulama dipojokkan untuk sekadar bertahan hidup dalam sistem. Sistem sekular menjamin pelaksanaan syariah di ranah pribadi. Pembangunan masjid dibantu. Dakwah khayriyah dipromosikan. Zakat dan haji dilayani pemerintah. Ulama yang terpojok akhirnya mengambil sikap, “Inilah yang masih bisa kita kerjakan.” Mereka akhirnya diam terhadap urusan publik yang masih diatur sistem kufur. Padahal kezaliman pada urusan ini (misalnya mahalnya BBM) melanda semua orang; Muslim atau bukan; apakah mereka tahu masalahnya atau tidak. Dakwah pun kemudian tak lagi untuk meluruskan penguasa yang bengkok, yang oleh Nabi saw. disebut sebagai afdhal al-jihâd (jihad paling utama), namun ”yang penting aman”.
Ketiga: Godaan 3-TA. Yang paling vulgar adalah pelemahan ulama dengan harta, tahta dan wanita. Ulama yang kesulitan finansial dibantu, pondoknya dibangun, santrinya diberi beasiswa, dan dakwahnya makin bernilai bisnis. Ada juga ulama yang dilamar jabatan, dari legislatif lokal hingga calon wapres. Yang terheboh tentu saja yang ditawari wanita. Namun, semua ada kompensasinya. Yang jelas kepekaan, sikap dan pengaruh politik yang bersangkutan bisa tergadai, atau setidaknya dia akan sibuk dengan 3-TA itu. Akibatnya, kinerja keulamaannya turun, atau bahkan dilupakan. Telah banyak pesantren yang hancur karena ditinggal pemimpinnya yang menjadi “selebritis” atau politisi di Senayan.
Adapun jebakan yang ilegal amat bergantung pada sikap penguasa. Kalau dia santun, ini tidak dilakukan. Dia mencukupkan diri dengan yang legal. Namun, penguasa zalim akan menempuh segala cara.
Pertama: pecah-belah. Adu domba ini tidak jarang dengan penyusupan intelijen. Fitnah dimunculkan: yang satu mencurigai yang lain; menuduh pihak lain sesat, ahli bid‘ah, dll. Akibatnya, ukhuwah islamiyah terputus.
Kedua: stigma negatif. Penguasa memberikan citra negatif seperti radikal, ekstremis dan teroris kepada ulama sehingga yang bersangkutan dijauhi masyarakat. Stigma ini umumnya ditujukan kepada ulama-ulama yang sederhana. Kadang-kadang jamaahnya dipancing untuk melakukan kekerasan, kemudian dimanfaatkan untuk mempertegas stigma yang diberikan.
Ketiga: siksaan dan penjara. Ini adalah cara terakhir untuk membungkam ulama. Namun, tren di negeri-negeri Muslim sekarang, ulama yang pernah disiksa atau dipenjara justru makin karismatik. Ini tidak disukai penguasa. Karena itu, direkayasalah seakan-akan sang ulama melakukan kriminalitas seperti menyimpan narkoba, melakukan kejahatan seksual atau pemalsuan dokumen; sebagaimana yang pernah divoniskan kepada Ustad Abu Bakar Baasyir.
Khatimah
Menyatakan seseorang atau sekelompok ulama telah terkena jebakan-jebakan di atas bisa menyulut emosi orang-orang yang merasa selama ini ikhlas berjuang dan berkonstribusi bagi umat. Mereka merasakan pahit-getirnya perjalanan dakwah. Sebagian bahkan telah menghabiskan usianya di penjara.
Semua itu tidak kita nafikan. Dengan menunjukkan jebakan-jebakan itu, kita tidak sedang menghakimi para ulama pada masa lalu, namun agar pada masa depan tidak ada dari kita yang kena sindiran Rasulullah saw.: Seorang Miuslim tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali.
Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []

 Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.
Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.
Bekerja di
Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.
Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.
Bekerja di