Belajar Membuat Undang-Undang
Ini termasuk Note yang sudah lama sekali ingin saya tulis, bahkan mungkin menjadi sebuah buku yang perlu dipelajari oleh mahasiswa FH, FISIPOL, FT dan FG. Juga pelajaran buat generasi muda geospasial. Mungkin saya tidak selesai menulis sekali, akan terus saya sempurnakan.
Tahun 2007, saya diminta masuk dalam sebuah tim beranggotakan 4 orang (“Tim 4 pendekar”) untuk membuatkan naskah akademis (NA) sebuah RUU. Karena RUU itu kini sudah jadi UU, maka saya sebut saja, itu UU Informasi Geospasial (UU 4/2011). Waktu itu, RUU itu sudah berusia 17 tahun (pertama kali digagas tahun 1990). Namanya masih RUU Tata Informasi Geografi Nasional (TIGNAS). Tapi “gagal maning-gagal maning”. 🙂 Konon salah satu penyebabnya adalah naskah akademisnya kurang mantap. Padahal konon naskah akademis itu sudah digarap oleh beberapa perguruan tinggi terkemuka, dibantu para senior di dunia survei dan pemetaan. Memang ini UU yang sangat teknis, mungkin lebih mirip UU lalu lintas lah … Kalau bahasa fiqihnya, ini bukan “Qanun Tasyri’i” tetapi “Qanun Ijra’i” – yakni peraturan yang dibuat cukup dengan kesepakatan, yang hukum syar’i asalnya bersifat mubah. Karena sifatnya teknis, maka saya tidak keberatan menggarap naskah akademisnya. Nanti saya ceritakan mengapa kalau non teknis koq saya mungkin keberatan.
Ya, dari Tim 4 Pendekar ini, semua lulusan teknik geodesi. Jadi semua insinyur! Tiga orang sudah Doktor! Semua masih di bawah 40 tahun. Dan semua lulusan luar negeri, saya dari Austria, teman-teman lain dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, ada juga yang ditambah sekolah di Jepang. Tentu saja ada pendamping dari Biro Hukum yang SH, tapi perannya di Naskah Akademis tidak besar. Belakangan saya minta ditambah 2 orang doktor geografi, keduanya juga alumni luar negeri (Jepang dan Jerman). Meski demikian, dalam perjalanannya, beberapa dari kami sempat diikutkan dalam training dan workshop legal drafting dari Kemenkumham.
LEGAL DRAFTING
Ketika kami mulai bekerja, tentu saja kami diberi bahan RUU yang sudah ada beserta NA yang pernah dibuat selama 17 tahun itu. Tetapi sejujurnya, ketika kami melihat RUU-nya, rasanya kalau makanan seperti “tanpa garam, tanpa sambal, tanpa lauk, dan tanpa nasi”. Lho memang makanan apa ya ? 🙂 Gak enak untuk ngomong “gak jelas”. Akhirnya Tim-4 ini memutuskan untuk melupakan RUU & NA lama itu, dan kami menuliskan semuanya baru. Metodenya, pertama-tama kami brainstorming, apa saja yang mau dimasukkan atau mau diatur. Persoalan apa di negeri ini yang mau dibantu dengan sebuah UU TIGNAS. Banyaklah. Misalnya tentang batas daerah yang samar-samar, peta antar instansi yang tidak sinkron dan tumpang tindih, peta mutakhir dan akurat yang sulit diperoleh, penanggulangan bencana tanpa bekal peta, penataan ruang yang carut-marut – termasuk petanya juga tidak karuan, dan sebagainya.
Setelah ada kumpulan masalah, kami mulai mencoba mengelaborasi, sebenarnya di dunia selama ini, masalah teknis tersebut diselesaikan dengan cara apa? Kami searching di internet, berbagai UU dan Peraturan lainnya dari Amerika Serikat, Canada, Belanda, Jerman, Austria, Australia, Malaysia, India, China, dan Jepang. Untung semua dari kami pernah sekolah di Luar Negeri. Dan untung sekarang ada Google beserta Google.Translates-nya 🙂 Mungkin ini studi banding yang paling murah dan komprehensif. Kami juga membaca banyak sekali UU dan RUU yang ada hingga saat itu. Kami mempelajari UU Nuklir (10/1997), UU UU Statistik (16/1997), UU Sipteknas (18/2002), UU Perencanaan (25/2004), UU Pemerintah Daerah (32/2004), UU Penanggulangan Bencana (24/2007), UU Penataan Ruang (26/2007), UU Wilayah Pesisir (27/2007), juga RUU Meteorologi & Geofisika, RUU Wilayah Negara, dan masih banyak yang lain. Saya kadang berharap, para Anggota DPR atau para Penegak Hukum itu pernah membaca UU lebih banyak dari kami. :-). Kemudian pokok-pokok pikiran itu dituliskanlah dalam sebuah RUU yang sama sekali baru. Kami sebut ini RUU #0.1. Kami juga membuat Naskah Akademisnya (NA #0.1). Pada awalnya, semua hal ini ditulis dalam sebuah matriks yang sangat besar. Setiap masalah, dihubungkan dengan sebuah pasal/ayat di RUU, lalu ada Keterangan sebagai naskah akademis, dan ada referensi yang menunjuk kepada suatu dokumen ilmiah atau UU/Peraturan di negara lain. Sebagai peneliti, kami bahkan membayangkan ada suatu Perangkat Lunak yang dapat mendukung pekerjaan legal drafting yang rumit ini sampai selesai. Mungkin namanya LDSS – Legal Drafting Support System. Tentu saja, akhirnya yang jadi produk akhir adalah dokumen RUU & Naskah Akademis.
Kedua dokumen ini kemudian di-floor. Pertama-tama tentu saja di internal Bakosurtanal sendiri. Kami meminta ada 3 jenis sesi. Sesi pertama adalah dengan para pejabat teras (eselon-1 dan eselon-2). Tentu saja, mereka biasa bicara pada level makro, tetapi umumnya hanya sensitif yang menyangkut unit kerjanya sendiri. Sesi kedua adalah dengan mid-management. Mereka umumnya lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan, tetapi juga hanya fokus pada unit kerjanya. Maka perlu sesi ketiga, yaitu dengan anak-anak baru, para PNS yang belum 5 tahun bekerja, masih fresh-graduate, tetapi umumnya memiliki idealisme dan passion dalam bekerja, juga belum terlalu fanatik pada unit kerjanya.
Kemudian keluar. Pertama adalah ke kalangan birokrasi. Kami mengundang semua Kementerian/Lembaga yang terkait dengan geografi. Yang paling sering adalah BPN, Kehutanan, ESDM dan PU. Kementerian Keuangan memiliki Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi seingat saya mereka tidak pernah hadir memenuhi undangan bedah RUU. Kedua adalah kalangan akademisi (Perguruan tinggi). Tim-4 beserta staf biro Hukum kemudian muter ke berbagai perguruan tinggi, terutama yang ada prodi yang terkait informasi geografis, seperti teknik geodesi, geologi, sipil, planologi, geografi, pertanian, kehutanan, kelautan dan sebagainya. Kadang mereka diundang ke Bakosurtanal. Ketiga adalah ke kalangan bisnis/praktisi yaitu kalangan profesional dan perusahaan-perusahaan yang terkait dunia geografi. Bisa perusahaan jasa pemetaan, bisa pula pengguna jasa survei pemetaan, seperti dari real estate, perkebunan dan sebagainya. Dan keempat adalah masyarakat umum, kami undang berbagai asosiasi profesi (ISI, IGI, MAPIN, IAGI, dll ) dan LSM (WALHI, JKPP, navigation.net, dsb). Materi RUU & NA juga kami share melalui berbagai blog dan milis.
Hasilnya, muncul ratusan kritik, masukan, usulan dan pertanyaan. Ini sebuah proses iterasi. Sampai hampir dua tahun kami bekerja menyempurnakan draft RUU & NA itu. Sampai akhirnya, draft itu dirasa matang (draft versi #1.0) untuk diserahkan ke Kemenkumham untuk harmonisasi.
HARMONISASI
Semua RUU di Republik ini wajib diharmonisasi, supaya tidak berbenturan dengan Konstitusi dan UU lain yang telah ada. Dan itu tugas Kemenkumham beserta Sekretariat Negara. Maka digelarlah sidang Harmonisasi di Kemenkumham. Mereka mengundang biro hukum dari semua Kementerian dan Lembaga yang terkait. Sebenarnya K/L terkait ini semua pernah kami undang, tetapi waktu itu orang teknisnya, bukan biro hukum. Nah, karena yang datang biro hukum, jadinya banyak hal yang harus dijelaskan dari awal lagi. Kaidahnya adalah: setiap UU harus bisa dipahami oleh orang yang awam teknis, tetapi melek hukum. Ternyata RUU #1.0 ini masih banyak cacatnya. Padahal sudah digodog hampir 2 tahun lho! Rapat harmonisasi memerintahkan dibentuk tim kecil, yaitu dari instansi pengusul (Bakosurtanal) ditambah pakar legal drafter dari Kemenkumham dan Setneg.
Oleh dua pakar legal drafter ini, seluruh RUU ini nyaris diformat ulang. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman membuat banyak UU yang bersifat teknis. Salah satu pakar ini konon juga ikut membidani UU Migas – karena Migas juga urusan Komisi 7 di DPR, sedang ristek (Bakosurtanal adalah lembaga di bawah Kemenristek) juga urusan Komisi 7. Secara substansi kami sudah pasrah. Para legal drafter itu yang menulis menurut struktur yang lazim. Tentu saja lazim menurut dia, karena kami melihat, style dari puluhan UU yang pernah kami baca itu memang lain-lain.
Tetapi ada juga substansi yang minta dipertegas. Ada beberapa pasal yang dinilai ambigu karena faktanya ada beberapa lembaga saat ini yang mengurusinya. Pakar dari Setneg ini minta “Sudah, semua diurus 1 Badan saja, kalau ada Lembaga lain yang terpaksa hilang 1 kedeputian, biarin saja, kan tupoksi mereka bukan itu”. Kami jadi terkejut dan perasaan campur baur. Belum sempat kami tenang kembali, beliau melanjutkan, “Namun nanti kalau dengan itu masalah pemetaan belum beres juga, semua tahu, siapa yang harus dicekik lehernya”. Jadilah pimpinan kami terkejut-kejut lagi … 😀
Selama harmonisasi ini kami juga berdebat panjang soal sanksi. Hanya UU yang ada sanksi yang akan dihormati. Maka kami diminta memikirkan, apa saja hal-hal yang masuk pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara atau denda? Apa ya? Akhirnya kami temukan juga. Misalnya, “secara tanpa hak memindahkan atau merusak atau membuat tidak berfungsi suatu tanda fisik jaring kontrol geodesi” — kalau yang paling gampang bentuknya adalah seperti pilar batas. Mau dihukum berapa juta Rupiah, atau berapa tahun? Wah berapa ya? Pakar yang kami undang dari Kejaksaan Agung mengusulkan 5 tahun! Alasannya, kalau 5 tahun atau lebih, itu bisa ditahan. Waduh, kasihan amat. Seorang pakar hukum pidana dari Ombudsman bertanya, apakah perbuatan itu jahat ya? Di dunia hukum sekarang ini, ada istilah “kejahatan” dan ada istilah “pelanggaran”. Menerabas lampu merah, itu bukan kejahatan, tetapi pelanggaran. Tetapi sebuah pelanggaran bisa menjadi kejahatan, kalau itu berakibat korban jiwa atau kerugian material orang lain. Tapi bagaimana menilainya ya? Kami diminta membuat simulasi, berapa sih kerugian bila ada pelanggaran bla-bla-bla … Pelanggaran yang berakibat lebih serius harus dihukum lebih berat.
Setelah setahun lebih, tinggal satu masalah: benturan dengan BPN. BPN kan melakukan pemetaan juga? Kami dipertemukan dalam rapat khusus dengan para pejabat BPN. Kami mempelajari semua UU dan peraturan yang ada di BPN. Ternyata tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa tugas utama BPN itu adalah membuat peta. Yang ada, mereka adalah mengurusi pertanahan. Jadi tidak masalah. Akhirnya dalam suatu rapat pleno di Kemenkumham, RUU ini dianggap Bulat dan Harmonis. Namanya diganti menjadi RUU Informasi Geospasial. Inilah RUU #2.0. RUU ini sah untuk dikirim Presiden (sebagai Pemerintah) ke DPR. Presiden menunjuk Menristek dan Menkumham, didampingi Kepala Bakosurtanal untuk menemui DPR.
PEMBAHASAN DI DPR
Jadilah, pertengahan 2010, RUU IG masuk Prolegnas. DPR, khususnya Komisi-7 mulai membuat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Filosofinya: UU itu kan mengatur rakyat. Sedangkan Pemerintah kemarin dianggap baru bicara-bicara dengan sesama birokrat. Memang harmonisasi itu hanya melibatkan birokrasi – jadi dianggap bukan rakyat. Sedang DPR itu wakil rakyat. Maka DPR mengundang rakyat. Tapi siapa ya? Meski DPR itu wakil rakyat, tetapi rakyat yang mana? Akhirnya, tim sekretariat DPR yang minta tolong kami untuk menunjukkan, rakyat yang terkait dengan RUU itu yang mana? Ya kami keluarkan saja daftar nama atau organisasi yang sebenarnya dulu pernah kami temui saat masih draft #0.1. Jadi ya orang-orang dari Perguruan tinggi, Kalangan praktisi dan LSM atau Organisasi Profesi itu diundang lagi. Tapi kini ke DPR.
Di RDPU, kami yang notabene dari birokrasi ini tidak diundang, tetapi kami boleh hadir di balkon. Tentu saja kami tidak boleh ikut bertanya, apalagi ikut menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari manapun. Para anggota dewan yang terhormat itu ingin bertanya ke rakyatnya, apakah RUU ini diperlukan tidak sih? Kalau diperlukan, substansi mana yang belum sreg? Ternyata, yang datang mewakili itu kadang tidak sama dengan yang dulu. Jadi masih muncul lagi ide-ide baru yang cukup bagus. Ada juga ide-ide yang disampaikan ke kami di luar sidang. Bahkan bahasanya sampai sambil ngancam, “Silakan, RUU ini disahkan, tetapi besoknya sudah saya bawa ke MK”. Sebenarnya, kami ingin mengadopsi ide-ide bagus itu ke RUU. Tapi itu tidak boleh begitu saja. Sekarang bolanya di DPR. Kalau RUU mau diedit lagi, ya Presiden harus menarik RUU itu dulu dari DPR, lalu Kemenkumham harus melakukan harmonisasi lagi. Wah ribet ya?
Tapi ada jalan keluar yang elegan. Para anggota dewan ini urusannya banyak. Mereka tidak cuma bertugas membuat UU yang seabreg, tetapi juga mengawasi pemerintah, mengontrol APBN, mendengarkan aspirasi konstituen dsb. Jadi, soal RUU IG ini mereka hanya punya waktu sangat sedikit. Oleh karena itu, mereka minta kepada staf ahli DPR untuk membuatkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Tentu saja, karena staf ahli DPR itu juga sangat sedikit, merasa kurang kompeten, sementara pekerjaannya bejibun, maka mereka minta bantuan kami, untuk membuat DIM. DIM ini nanti yang akan ditanyakan oleh anggota DPR ke Pemerintah. Di depan DPR, itu yang boleh menjawab adalah Menteri, dan paling rendah pejabat Eselon-1. Dan eloknya, karena kami ini notabene juga staf pemerintah, maka kami juga diminta oleh boss kami itu, untuk membuatkan jawaban atas DIM itu. Jadi kami ini yang sudah membuatkan RUU & NA, diminta juga membuatkan soal-soal DIM beserta jawabannya sekaligus. Sedang aktornya adalah DPR dan pemerintah. 🙂
Tapi itu cara yang dapat memberi peluang kami untuk terus memperbaiki RUU. Jadi pura-puranya DPR akan tanya, “Kenapa pasal anu koq bunyinya begitu, bagaimana kalau begini saja (modifikasi)”. Dan pemerintah nanti akan merespon, “Itu saya kira masukan yang sangat bagus dari Dewan, dan kami Pemerintah setuju”. Nah, jadinya RUU yang jadi nanti akan lebih bermutu.
Tapi taqdir ternyata berkata lain. Ada 3 hal yang di luar perhitungan kami:
Pertama, oleh DPR, ternyata DIM itu dipecah-pecah sampai setiap ayat. Jadi, satu pasal yang mengandung 5 ayat, bisa di-“mutilasi” menjadi 6 DIM, yaitu satu untuk judul dan total 5 dari tiap ayatnya. Terus Komisi 7, dalam suatu rapat marathon yang sangat cepat, membagi-bagi tiap nomor DIM itu apakah “tetap”, atau “dibahas di Panja”, atau cukup “dirumuskan ulang di TimMus-TimSin”. Panja adalah Panitia Kerja, yaitu separuh dari anggota Komisi-7 yang sekitar 50 orang itu. Sedang TimMus adalah Tim Perumus, yaitu separuh dari Panja. Dan TimSin adalah Tim Sinkronisasi, yaitu separuh dari TimMus. Karena “mutilasi” ini dibahas sangat cepat, kadang-kadang jadi lucu: ada pasal yang judulnya diminta dibahas di Panja (jadi ada kemungkinan berubah), tetapi salah satu ayatnya dibilang tetap, atau sebaliknya. Ini baru dalam pasal yang sama, belum kalau beberapa pasal pada bagian atau bab yang sama.
Kedua, oleh staf DPR, setiap item DIM tadi yang sudah kami siapkan soal-jawabnya, “dibagi rata” ke semua fraksi. Ada 9 fraksi di DPR. Akibatnya, ada satu pasal yang DIM untuk ayat 1 dan 2 – misalnya – untuk Partai Demokrat, tetapi ayat 3 dan 4 untuk PDIP, dan ayat selanjutnya untuk Gerindra. Kesatuan di dalam pasal jadi kacau. Lebih ruwet lagi, pada saat sidang, fraksi-fraksi kecil seperti Gerindra atau Hanura jarang hadir! Mereka hanya punya sedikit wakil di DPR. Giliran yang ngomong Demokrat, wakil dari PDIP komentar, “Lho, ini koq Partai Demokrat (PD), yang notabene partai pemerintah malah mengkritik RUU dari pemerintah sendiri?”. Yang dari PD tadi jadi kurang PD (percaya diri). Jadinya dia malah berkata, “Ya ini bukan kritik, tetapi apresiasi dan hanya sedikit masukan”. Jadilah, beberapa item yang bagus untuk perbaikan RUU itu, yang kebetulan ada di kantong Gerindra dan Demokrat, urung disampaikan.
Ketiga, pada masa pembahasan RUU ini, jajaran eselon-1 di Bakosurtanal berganti total. Orang-orang baru ini yang akhirnya berhadapan dengan Panja di pembahasan. Kami dari tim sudah menyiapkan suatu teknologi agar mereka yang duduk di depan dan berhak menjawab, dapat dengan mudah kami beri contekan. Teknologi ini berbasis laptop dan jaringan wifi terbatas. Tapi dalam perjalanannya, rupanya antara grogi atau terlalu percaya diri (tapi keliru) bercampur aduk, sehingga kadang-kadang hasilnya tidak optimal. Ya mohon maaf, sekali lagi, dalam pembahasan dengan DPR ini, tim penyusun RUU & NA (“Tim 4 pendekar” yang sudah menjadi “Tim 6 pendekar”) tidak boleh ngomong, kecuali diminta oleh ketua sidang.
Jadilah ada beberapa item yang semula sangat “reformatif”, tiba-tiba “orde baru” lagi. Misalnya, hingga versi #2.0, masih ditulis bahwa “informasi geospasial dasar, bersifat terbuka, dan dalam format elektronik dapat diakses masyarakat dengan 0 Rupiah (=gratis)”. Tetapi kalimat ini kemudian direlatifkan lagi oleh DPR dengan kalimat “DAPAT dikenakan biaya tertentu yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sekarang ini masyarakat yang akan mendapatkan peta memang dikenai tarif yang diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi bahasa kasarnya, DPR ini mau bilang begini, “PNBP ini kan bisa menghasilkan uang – kenapa malah mau kalian hapuskan, nanti kalian minta uang lagi ke DPR?”.
Pembahasan dengan DPR kadang dilakukan di gedung DPR. Acara ini terbuka, boleh diliput wartawan. Saya amati, pas di DPR, persidangan hanya memiliki speed kira-kira 1 ayat per jam. Artinya sangat alot. Setiap anggota panja ingin ngomong, dan harus diakomodir ketua sidang. Anggota dewan itu ada yang mengaku sudah dua puluh tahun dipercaya mewakili rakyat, dan sudah membuat 50 Undang-undang, jadi jangan sampai merasa diremehkan. Artinya, dalam sehari kadang hanya selesai 1 pasal. Padahal ada puluhan pasal. Tetapi kalau – dengan alasan perlu sidang yang lebih intensif – kemudian sidang dilanjutkan di hotel, walaupun judulnya terbuka, tetapi tidak ada wartawan, sidang bisa memiliki speed 10 pasal per jam !!!
Ini realita. Tetapi setelah semua pasal dibahas, RUU ini tidak bisa begitu saja diketok. Rupanya ada satu syarat menurut Tata Tertib DPR yang belum terpenuhi, yaitu: STUDI BANDING. Ya, dan studi banding yang dimaksud adalah ke luar negeri! Yang sudah studi banding via internet dan pengalaman semasa studi kan kami (Tim 6 Pendekar), sedangkan mereka anggota Dewan kan belum. Jadilah, mereka minta studi banding, dan negaranya juga mereka yang menentukan: USA dan Jerman!
Sebenarnya kalau dari segi kemiripan dengan Indonesia, maka yang paling mirip secara geografis itu Jepang (sama-sama negara kepulauan dengan banyak gunung api dan kota-kota yang padat penduduk). Sedang secara demografis itu China atau India (sama-sama negara berkembang dengan penduduk yang sangat banyak). Tetapi kalau anggota Dewan pingin ke USA atau Jerman, ya harus nurut … kecuali kita tidak ingin RUU ini selesai.
Rencana Studi Banding ini sempat tertunda dua kali. Pertama gara-gara gunung Merapi meletus. Jadi tidak elok, lagi ada bencana koq DPR malah “plesiran”. Yang repot para pendamping ini. Karena ingin tiket murah, jadinya ketika di-reschedule, kena fee yang cukup besar, jadi malah mahal. Penundaan kedua gara-gara ada sidang Paripurna membahas hasil Pansus Century & Pansus Pajak. Semua anggota wajib hadir! Jadinya, jadwal yang sudah dirancang baik-baik, termasuk ketemu Parlemen Jerman atau US-Congress, gagal total. Padahal sangat sulit membuat jadwal dengan mereka, karena sebentar lagi mereka juga reses.
Tetapi akhirnya jadilah kami merencanakan tour ke Jerman dan USA, walaupun versi minimalis. Saya diminta mengawal yang ke Jerman. Mereka rencana jalan 5 hari, berangkat Minggu, efektif di Jerman mulai Senin sampai Jum’at, lalu pulang Sabtu pagi. Mungkin kami memang serius ya, jadi lima hari itu benar-benar padat. Sampai di Berlin sudah Senin siang, setelah makan siang kami langsung diterima di KBRI, diteruskan dengan dinner. Karena jetlag, setelah itu sudah ngantuk sekali. Selasa pagi, kami diterima Kementerian Ekonomi & Teknologi; lalu sorenya ke Geoforschung Potsdam (ini seperti Badan Geologi Jerman). Rabu pagi naik kereta api ke Frankfurt. Sampai Frankfurt sudah siang, setelah lunch, langsung ke Bundesamt fuer Kartografie & Geodaesie (semacam Bakosurtanal-Jerman). Kamis pagi naik kereta api lagi ke Muenchen. Sampai juga sudah siang. Setelah lunch, baru ke Deutsche Luft & Raumforschung (semacam LAPAN-Jerman). Baru hari Jum’at ada sedikit waktu untuk jalan-jalan. Ternyata terlalu banyak keinginan. Ada yang ingin ke stadion Bayern-Munich, ada yang ingin menyeberang ke Innsbruck (Austria), ada yang ingin ke Switzerland (yang semua tidak terlalu jauh dari Muenchen). Eh, busnya malah mesinnya rusak. Baru jam 10.30 beres, lalu ke Innsbruck, di sana cuma 2 jam, balik lagi. Sampai Muenchen sudah malam. Habis dinner, tinggal ada waktu 30 menit untuk belanja oleh-oleh sebelum tokonya tutup. 😀
Selama perjalanan kami sempat menyaksikan tingkah laku anggota Dewan yang ikut dalam tour. Ada yang serius memperhatikan penjelasan dari mitra kita di Jerman. Ada yang sibuk telponan terus dengan konstituennya di Indonesia. Sepertinya, kadernya baru mau maju pilkada di suatu daerah. Ada juga istri anggota Dewan (jadi bukan anggotanya) yang sibuk memarahi kader partainya yang jadi bupati di beberapa daerah. Saya dengar dari staf ahli, ternyata beliau inilah penyandang dana terbesar partai itu. Ada anggota Dewan dari suatu partai berbasis masa agama yang rajin ngebanyol. Sepertinya di rapat dia tidak pernah ngomong, tetapi setiap kali acara makan isinya ngebanyol melulu. Tetapi ada juga anggota Dewan yang rajin bertanya ke saya, “Ada gak ya pasal yang bisa kita titipin?”. Saya tanya, “Maksudnya?”. “Ya kita buat ada semacam pemberian konsesi begitu, nanti yang masuk ya kita juga … “. Maklum, Komisi-7 yang mengurus migas ini juga diisi beberapa pengusaha yang mendapat konsesi minyak. Jangan meremehkan seorang anggota dewan yang kesana kemari cuma pakai sarung dan peci, karena diam-diam dia bisa punya konsesi beberapa sumur minyak. Alamak ….
Setelah itu draft digodok terakhir di TimMus dan TimSin. Idealnya di sini tidak boleh lagi ada substansi yang berubah. Ada ahli bahasa yang bertugas memastikan bahwa pilihan kata yang dipakai benar. Dan ada pakar UU yang memastikan bahwa UU itu sinkron dengan semua UU lain yang telah ada. Namun dalam perjalanan sidang, ketemu lagi beberapa hal yang kalau diubah, ya berpengaruh pada substansi. Walah … Tapi ya sudahlah, diselesaikan “secara adat”. Toh anggota TimMus / TimSin juga anggota Panja. Pada jam-jam terakhir – sudah larut malam – salah satu wakil fraksi yang juga seorang Kyai berkata begini, “Tuhan saja, perlu menurunkan 25 nabi hingga peraturannya sempurna. Jadi kalau kita baru sekali ini koq belum sempurna, ya tidak usah terlalu kecewa”. Mungkin ini guyonan Kyai yang bertugas di DPR. Inilah RUU versi #3.0.
Beberapa hari sebelum masa sidang habis (untuk setiap RUU hanya ada jatah 3 kali masa sidang), seorang anggota DPR minta kami menghadirkan unsur Kemenhan & TNI, karena dikhawatirkan nantinya militer ini tidak mau nurut sama UU yang dibuat sipil. Ada interupsi dari anggota lain yang mengatakan, siapapun warga negara ini wajib mentaati semua produk UU, apakah itu sipil atau militer. Tetapi kami tetap berusaha menghadirkan unsur militer terkait. Sampai malam kami melobby para jenderal dari Dinas Topografi Angkatan Darat (Dittopad), Dinas Hidrooseanografi Angkatan Laut (Dishidros-AL) dan Dinas Survei dan Pemotretan Udara Angkatan Udara (Dissurpotrud-AU) agar mereka mau hadir sendiri (tidak mewakilkan) di DPR saat RUU itu diketok. Alhamdulillah, ketiga jenderal itu semua mau hadir. Menjelang hari draft RUU diketok di Pleno Komisi-7, malamnya saya dan satu anggota Tim-6 ditelepon untuk datang ke DPR pukul 6 pagi. Ada beberapa item lagi yang ingin dimasukkan oleh anggota Dewan. Ada yang di teks, dan ada yang di penjelasan. Kami benar-benar tegang. Sampai akhirnya RUU itu diketok, dan beberapa hari kemudian di Paripurna diketok juga, jadi UU no 4/2011 tentang Informasi Geospasial.
Tapi pekerjaan kami belum selesai. Ada 7 Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 Peraturan Presiden (Perpres) yang harus dibuat sebagai turunan UU itu. Ada waktu 2 tahun sampai April 2013 ini. Tapi membuat PP dan Perpres tidak seheboh bikin UU. Dan yang jelas tidak perlu pakai Studi Banding segala. 😛
Tags: DPR, membuat undang-undang, undang-undang, uu

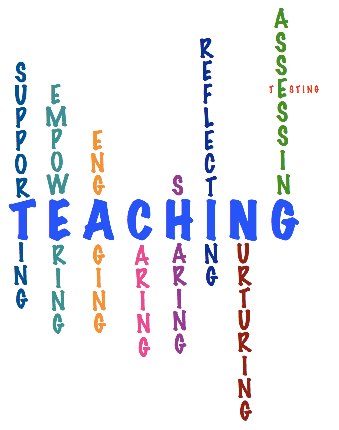
 Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.
Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.
Bekerja di
Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.
Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.
Bekerja di