Beyond the Scientific Way
Belajar Menjadi Guru, Dosen, Widyaiswara, Ustadz …
Friday, January 4th, 2013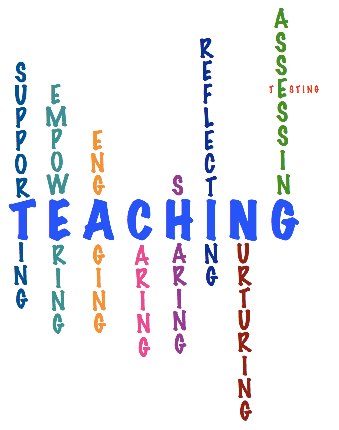 Siapakah guru dalam hidup Anda yang paling Anda kagumi?
Siapakah guru dalam hidup Anda yang paling Anda kagumi?
Apa yang sangat menginspirasi dari guru Anda itu?
Guru adalah salah satu profesi yang paling dikenal anak-anak. Sangat banyak anak punya cita-cita jadi guru, selain mungkin jadi dokter, insinyur atau pilot. Tetapi ketika mereka semakin besar, semakin kenal dengan kenyataan kehidupan guru, semakin sedikit yang masih mempertahankan cita-cita ini. Baru akhir-akhir ini saja, profesi guru “booming” lagi. Itu setelah di berbagai daerah, guru mendapat tunjangan profesi 1x gaji. Akibatnya, FKIP di berbagai kampus menjadi favorit, bahkan di beberapa kampus, persaingannya mengalahkan FT atau FE.
Sejujurnya, saya termasuk yang tidak pernah punya cita-cita jadi guru. Kalau jadi ilmuwan ya. Tetapi ternyata perjalanan hidup saya menyebabkan saya melewati fase menjadi guru, juga dosen, widyaiswara, dan bahkan ustadz 🙂 Walaupun semua mungkin pakai embel-embel “Luar Biasa”.
Saya pertama kali “pura-pura” jadi guru, itu kelas 2 SMP, ketika di sekolah, guru sejarah saya mencoba menerapkan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Anak-anak diminta membentuk kelompok @ 4 orang, lalu masing-masing diberi tugas suatu bab di buku paket, lalu “mengajar” siswa yang lain di depan kelas, bahkan sampai memberikan test. Tetapi seingat saya tidak semua kelompok sempat maju, karena waktu keburu habis. Saya beruntung termasuk yang sempat tampil, bahkan saya yang didaulat untuk yang berdiri mengajar di depan kelas.
Setelah itu ternyata saya jadi sering “mengajar” untuk berbagai hal yang lain. Mengajar PKS (Patroli Keamanan Sekolah), lebih tepatnya mungkin disebut Melatih. Sebelumnya saya dan beberapa kawan dilatih menjadi anggota PKS oleh Polres. Tugas PKS itu yang terpenting seperti Polantas, tetapi khusus untuk menyeberangkan anak-anak sekolah di depan sekolah. Maklum tenaga polisi saat itu dirasa terbatas. Setelah itu, beberapa kali seminggu, pagi pukul 6.30 kami sudah bertugas. Setelah praktek beberapa bulan, sekolah merasa perlu regenerasi, sehingga kami melatih adik-adik kelas.
Setelah PKS, pengalaman menjadi “guru” yang lebih panjang ada di Pramuka dan KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) di SMA. Walaupun kalau direnung-renungkan sekarang, banyak “pelajaran” di Pramuka saat itu yang “nggak mutu”, tapi dulu koq ya percaya diri saja ya … he he … Kalau KIR agak mending. Sampai sekarangpun saya kira masih banyak pelajaran yang relevan, bahkan tidak cuma untuk siswa SMA, bahkan untuk sarjana yang lagi meniti karier jadi peneliti muda 🙂
Sewaktu saya kuliah di Austria, saya juga punya pengalaman beberapa kali jadi “guru”. Pertama “guru” internet. Ini terjadi tahun 1995, sewaktu penggunaan internet masih relatif awal. Mungkin ini lebih tepat disebut “tutorial”. Kedua tahun 1996, “guru” bahasa Indonesia untuk orang asing. Ternyata rumit juga mengajar bahasa Indonesia yang sistematis untuk orang bule. Murid-murid saya saat itu ada 3 kelompok motivasi. Pertama yang motivasinya pekerjaan, yakni mereka akan dikirim bekerja di Indonesia (biasanya teknisi atau personil bisnis pariwisata). Kedua yang motivasinya travelling. Ada murid saya yang profesinya Profesor Fisika, tetapi hobby travelling, dan liburan mendatang ingin “blusukan” mengelilingi Indonesia. Alamak, waktu itu saya juga belum pernah keliling Indonesia. Yang lucu yang ketiga, motivasinya keluarga. Ada murid saya, wanita Austria yang akan menikahi pria Indonesia. Jadi dia perlu belajar banyak hal agar keluarganya harmonis.
Tahun 1997, sepulang dari Luar Negeri, beberapa saat lamanya saya diminta mengajar di sebuah kursus programming di suatu perusahaan. Mereka minta diajar programming dalam Visual Basic. Sejujurnya, saat saya meng-iyakan, saya belum pernah lihat Visual Basic. Saya memang punya pengalaman programming yang cukup panjang dalam C, Pascal, Fortran, Lisp, SQL dan Basic. Tetapi Visual Basic? Akhirnya saya praktis hanya menang 1 minggu dari peserta. Tetapi alhamdulillah dalam waktu singkat saya sudah lumayan expert. Repotnya ketika di akhir kursus, ada peserta yang tanya, apakah saya sudah punya “Microsoft Certified Programmer” ? Saya menjawab diplomatis, “Sepertinya Bill Gates juga belum punya tuh? ” 🙂
Karena saya sudah mengantongi gelar Doktor, maka mulailah saya beranjak dari “guru kursus” ke dosen. Ada prodi S1 suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meminta saya masuk dalam tim dosennya. Teorinya, kalau saya masuk, ijazah S3 dan sejumlah publikasi saya bisa mendongkrak nilai akreditasi BAN-PT untuk prodi di PTS tersebut. Ternyata betul. Bahkan waktu itu, prodi di PTS tersebut terakreditasi lebih dulu dari PTN pembinanya !!! Tetapi setelah terakreditasi, tiba-tiba jumlah mahasiswa yang diterima PTS itu berlipat 3x. Dosennya yang kewalahan. Kalau cuma mengajar sih mungkin tidak terlalu berat. Tetapi kalau harus mengoreksi tugas, wow … capek dech … Apalagi mengajar di LCU (Low Cost University) ini harus lebih banyak ibadahnya … 🙂 Lima tahun kemudian, karena saya semakin sibuk di kantor, saya makin mengurangi jam mengajar saya di PTS tersebut, sampai akhirnya off sama sekali.
Saat itu saya juga mencoba menjadi dosen program S2 di IPB dan di UPM (Universitas Paramadina Mulya). Yang S2 di IPB ini program internasional, wajib pakai bahasa Inggris. Sedang yang di UPM kelas eksekutif, jadi kuliahnya malam. Sangat berbeda dengan S1, menjadi dosen S2 jauh lebih “santai”. Mahasiswanya tidak banyak, tetapi honornya banyak … he he … Kadang saya berpikir, jangan-jangan honor saya ngajar S2 ini sebenarnya untuk jerih payah ngajar S1 di LCU itu … 🙂 Yang jelas, ndosen di S2 bersama para eksekutif itu membuat kita jadi terus terasah. Kita mengakumulasi berbagai pengalaman dan wawasan.
Meski menjadi selingan yang menggairahkan, tetapi karena saya secara resmi bukan dosen, maka kadang-kadang tugas ini sedikit “terganggu”. Yang paling ringan adalah ketika tiba-tiba ada jadwal rapat yang berdekatan dengan jadwal mengajar. Kadang-kadang sulit kita mencari waktu pengganti. Yang lebih repot lagi adalah ketika kita punya atasan yang kurang suka atau bahkan tidak setuju kita “ndosen” pada jam kerja. Dianggapnya itu buang-buang waktu, atau bahkan “korupsi waktu”. Padahal sesungguhnya, pada saat mengajar, kita juga bertambah ilmu, dan juga memperluas jejaring, yang juga memiliki multiplier effect pada tugas-tugas kita di kantor. Mahasiswa S2 itu berasal dari berbagai daerah, berbagai lembaga, juga berbagai profesi dan latar belakang.
Ada beberapa kampus yang secara tersirat menawari saya pindah, jadi dosen full-time saja di sana. Mereka mengatakan, kalau jadi dosen full-time nanti bisa jadi Professor. Waktu itu saya coba hitung-hitung angka kredit kumulatif saya kalau dihitung sebagai dosen. Ternyata jauuuh. Terutama karena saya tidak bisa memenuhi porsi tri-darma perguruan tinggi yang pertama yaitu pendidikan/pengajaran. Ya maklum, ngajar di sana-sini cuma 2 SKS. Paling total cuma 6 SKS per semester … Kalau mau “ngebut”, mesti menulis buku ajar. Sebenarnya menulis buku ajar tidak terlalu susah, karena tidak harus penemuan sendiri. Bisa menggubah ulang apa yang pernah ditulis orang lain. Tetapi sepertinya saya nggak bisa menuliskan sesuatu yang tidak pernah saya dalami sendiri. Untunglah, kemudian muncul SKB Mendiknas-Kepala LIPI-Menpan yang mengesahkan adanya Profesor Riset, yakni jenjang Professor yang menjadikan riset sebagai komponen utama.
Selain itu, untuk berbagai diklat dari berbagai kementerian/lembaga saya juga diminta menjadi “Widyaiswara Luar Biasa”. Widyaiswara agak berbeda dengan dosen, karena yang dididik bukan mahasiswa (apalagi mahasiswa S1), tetapi orang dewasa yang kadang merasa sudah lebih berpengalaman, atau bahkan merasa “untuk apa harus ikut diklat lagi, toh sudah tua dan sebentar lagi pensiun”. Jadi perlu pendekatan yang berbeda, bahasa kerennya “Andragogi”, bukan “Pedagogi”. Di diklat yang diadakan Bakosurtanal/BIG, saya kadang menjadi WLB untuk bidang Pemetaan, Penegasan Batas, Penataan Ruang, Penanggulangan Bencana dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Di LIPI saya menjadi WLB Diklat Fungsional Peneliti tingkat Lanjut. Jadi WLB ini tidak terlalu stress, karena kita cukup banyak cerita dari pengalaman kita saja, dan gak usah bikin soal yang rumit seperti ujian mahasiswa. Biasanya sih – asal tidak keterlaluan – semua peserta diklat akan lulus. Toh terserah mereka, apakah ilmu yang kita berikan akan terpakai atau tidak pada lingkup pekerjaan mereka.
Yang terakhir setelah guru – dosen – widyaiswara, itu adalah ustadz. Ini seharusnya pos yang paling tinggi. Di Mesir itu, lulusan S1 syari’ah tidak langsung dipanggil Ustadz, tetapi “Mu’id”. Nanti kalau sudah S2, dia akan dipanggil “Musaid Mudaris”. Setelah S3 dipanggil “Mudaris”. Setelah mengajar dan riset kira-kira 5 tahun, akan dipanggil “Musaid Ustadz”. Baru setelah 10 tahun sejak S3, kalau angka kumnya tercapai dan senat setuju, akan dipanggil “Ustadz”. Jadi rupanya Ustadz itu sama dengan Professor. Tetapi di Indonesia, panggilan Ustadz bisa dicapai siapa saja. Sangat egaliter. Dan tahukah Anda, bahkan sejak saya masih SMP, saya sudah dipanggil “Ustadz” !!! Itu terjadi lantaran saya membantu mengajar membaca al-Qur’an belasan anak-anak kecil di masjid kampung. Kemudian menggantikan ayah saya yang wafat mengisi majlis taklim Ibu-ibu. Kemudian mengisi khutbah di sekolah. Tentu saja, sebagai “Ustadz” tingkah laku kita lalu juga jadi sorotan. Tapi ini bagi saya tidak masalah. Ketika saya pada usia 26 tahun sudah naik haji, tambah disorot lagi !!! Karena banyak orang yang menunda naik haji, karena takut nggak bisa “membuat dosa” lagi … Itu tanda orang yang kurang cerdas. Karena, kata Imam Ghazali, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati, dan kematian bisa datang kapan saja, tidak nunggu tua. Karena itu, ayo buruan jadi “Ustadz” — mumpung di Indonesia belum perlu syarat macam-macam seperti di Mesir – asal tahu diri saja kapasitas ilmunya … 🙂
Tapi fenomena “Ustadz TV” atau “Ustadz Google” akhir-akhir ini memang agak memprihatinkan. Seorang dianggap ustadz hanya oleh aktivitas ceramahnya, dan bahannyapun “cuma disedot dari Google”. Padahal aktivitas Ustadz – dan juga guru/dosen/widyaiswara pada umumnya – yang hakiki itu adalah MENGUBAH (CHANGE). Mengubah dari mindset (pola pikir), kemudian behaviour (perilaku), dari yang kurang cerdas menjadi cerdas, dari yang kurang cekatan menjadi cekatan, dan dari yang kurang islami menjadi islami – sesuai syari’ah. Percuma saja ngustadz di TV, ditonton jutaan orang, kalau tidak satupun yang berubah, karena isinya cuma banyolan. Lebih gawat lagi, kalau isinya memang mengubah, tetapi malah mengubah jadi makin tidak islami. Karena orang yang tersesatkan akan berkilah, “Lho ini kata Ustadz Fulan di TV hukumnya halal koq”. Padahal “fatwa halal” Ustadz Fulan itu ternyata cuma pakai “dalil perasaan”, kalau tidak “katanya” ya “pokoknya”.
Baik guru, dosen, widyaiswara maupun ustadz, semua memiliki tanggungjawab sampai akherat sana. Karena itu beruntunglah mereka yang memposisikan semua amal itu untuk ibadah, bukan sekedar untuk mencari penghidupan. Kita tidak usah risau dengan kompensasi yang kadang tidak sesuai dengan jerih payah, karena “Gusti Allah ora sare” (Tuhan tidak pernah tidur). Dia Yang Maha Adil tidak akan pernah membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Hal Jazaa’ul Ihsani Illal Ihsan”.
Salam.
Belajar Beberapa Bahasa Asing
Monday, December 31st, 2012Berapa bahasa asing yang Anda kuasai?
Berapa tahun Anda belajar bahasa tersebut?
Apakah Anda percaya diri berkomunikasi dengan bahasa itu?
Sekarang ini, banyak orang menawarkan training untuk menguasai bahasa asing. Ada yang dengan jargon “Enam minggu percaya diri berbahasa Inggris”. Ada juga bahkan “Enam jam percaya diri berbahasa Inggris” … Anda percaya, dan mau keluar uang untuk ikut kursus itu?
Saya tidak menampik bahwa ada orang-orang yang memang dikarunia kecerdasan linguistik yang luar biasa. Sewaktu di Austria, saya mengenal seorang Profesor kimia yang memiliki hobby bahasa. Beliau menguasai secara aktif 10 bahasa asing, yaitu (kalau tak salah 🙂 Jerman (bahasa ibu) – Inggris – Perancis – Spanyol – Italia – Turki – Arab – Jepang – China – Thai. Dan dia waktu itu ingin belajar bahasa Indonesia dengan kami – mahasiswanya.
Tetapi mayoritas atau rata-rata orang, memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menguasai satu bahasa asing saja. Di sekolah, anak-anak kita sejak kecil diberi pelajaran bahasa Inggris, bahkan di SDIT juga bahasa Arab. Kalau mereka lulus SMA, mereka telah menelan 12 tahun pelajaran bahasa Inggris dan 12 tahun bahasa Arab? Apakah mereka sudah bisa kita ajak ngobrol atau surat menyurat dengan bahasa itu? Jawabnya pasti: tergantung ! Tetapi saya mengamati: mayoritas tetap tidak percaya diri.
Sebagai orang yang lahir di Jawa Tengah, bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa. Kemudian, di kelas 1 SD, pelan-pelan saya mulai belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hanya dua bahasa itu yang diajarkan di SD saya saat itu.
Di rumah, karena ayah saya mahir bahasa Arab, saya dilatih small-talk bahasa Arab. Kalau ada tamu yang juga ustadz atau kyai, ayah saya suka memamerkan “kebolehan” saya bercakap-cakap ringan dalam bahasa Arab. Namun pelajaran bahasa Arab ini kemudian terhenti ketika ayah saya sakit, bahkan lalu meninggal dunia.
Di SMP-SMA kita semua belajar bahasa Inggris. Tetapi saya kira, guru-guru kita sendiri masih baru “teaching as usual”. Di SMA bahkan salah satu guru bahasa Inggris saya hanya menekankan grammar. “Conversation itu tidak akan keluar di EBTANAS ataupun Sipenmaru”, katanya. Wow … bener juga sih.
Pada saat kelas 2 SMA, saya pernah ikut test seleksi peserta American Friendship Service (AFS). Ujiannya 3x. Ujian pertama: pengetahuan umum dan mengarang dalam bahasa Inggris. Yang lulus, ikut ujian ke-2: Wawancara dalam bahasa Indonesia (tentang motivasi ikut AFS) dan Wawancara dalam bahasa Inggris. Yang lulus, ikut ujian ke-3: diskusi kelompok (dalam bahasa Indonesia). Sewaktu ujian pertama mengarang dalam bahasa Inggris, saya menulis seluruh karangan saya terlebih dulu dalam bahasa Indonesia, baru menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Saya kira karangan saya jelek sekali. Tetapi saya lolos ke ujian ke-2. Wawancara dilakukan oleh anak AFS dari Amerika yang sekolah di Indonesia. Sepertinya sedikit nyambungnya … he he … tetapi saya beruntung lolos ke ujian ke-3. Diskusi kelompoknya membahas isu-isu kontroversial. Tapi dari sekian belas orang yang sampai ujian ke-3 ini hanya dipilih 1-2 orang saja. Dan saya alhamdulillah tidak terpilih !!! Kalau saya terpilih, mungkin jalan hidup saya akan sangat berbeda.
Ketika baru duduk 1 semester di ITB, saya lolos tes beasiswa LN OFP-Ristek, sehingga saya dipanggil untuk kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Seperti diketahui, bahasa yang dipakai di Austria adalah bahasa Jerman, sama seperti di Republik Federasi Jerman dan Swiss. Hanya di Swiss, bahasa resminya ada 4, selain Jerman juga Perancis, Italia dan Ratoroman.
Di Goethe Institut kami belajar 5 jam sehari x 5 hari/minggu. Bahasa Jerman diajarkan dengan pengantar bahasa Jerman juga. Kami cuma dikasih Glosarry, seperti kamus tetapi tidak urut abjad, melainkan urut kata-kata yang keluar selama pelajaran. Gurunya separo orang Indonesia dan separo orang Jerman. Tidak semua orang Jerman bisa jadi guru di Goethe Institut lho, mereka harus lulus sekolah mengajar bahasa Jerman untuk orang asing.
Setelah dua minggu kursus, kami kedatangan seorang Profesor dari Austria yang akan mewawancarai kami. Tahu kami baru kursus dua minggu, dia coba menanyai kami dalam bahasa Inggris. Tetapi ternyata, dengan kursus dua minggu itu, bahasa Inggris yang telah saya pelajari enam tahun, seperti terhapus oleh bahasa Jerman.
Setelah kursus sekitar lima bulan, kami menghadapi ujian Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF). Mungkin mirip TOEFL. Bentuk ujiannya ada 5: LV (Leseverstehen – Membaca & Memahami), HV (Hoerverstehen – Mendengar & Memahami), SA (Schriftliche Ausdruck – Mengarang), SW (Strukturen & Wortschatz – Tatabahasa & Kosakata) dan MA (Mundliche Ausdruck – Berbicara). Saya mendapat nilai 96,5 (dari max 120). Wah jadi sangat percaya diri.
Sampai di Austria, kami dikursuskan bahasa Jerman level Universitas, karena agar diterima di Universitas, setiap mahasiswa asing harus lulus Universitaet SprachPruefung (ujian bahasa universitas). ZDaF saja tidak cukup. Alhamdulillah, setelah dua bulan, saya mengantongi ijazah USP ini.
Kuliah pun dimulai. Dari 70-an mahasiswa, yang orang asing cuma 2 orang, termasuk saya. Stress-pun dimulai. Waktu itu, proyektor LCD + Powerpoint belum ada. Dosen paling hanya memakai OHP, tetapi lebih banyak yang menulis mind-map-nya di papan tulis. Saya yang jadi bingung, apa yang mau ditulis, apalagi ternyata banyak dosen yang ngomongnya secepat kereta api. Akhirnya saya selalu duduk di samping mahasiswa bule. Kalau dia nulis, saya ngelihat apa yang dia tulis, kalau perlu tanya, lalu saya tulis juga. Saya tidak akan fotocopy. Memang mungkin terlihat kekanak-kanakan buat saya, dan agak mengganggu bagi si bule, tapi ya itulah yang harus saya jalani beberapa bulan. Lebih repot lagi, ada mata kuliah Pengantar Hukum Konstitusi dan Administrasi (Verfassung & Verwaltungsrecht) yang dosennya tidak pernah menulis. Dia datang, duduk di meja, lalu cerita. Akhirnya saya menghadapnya, tanya buku apa yang paling praktis untuk saya baca agar saya mengerti apa yang dia ajarkan. Buku itu lalu saya cari di perpustakaan, kemudian saya membaca semua bab sebelum dia ajarkan. Hasilnya, di akhir semester, saya malah mendapat nilai tertinggi untuk mata kuliah itu.
Sejak di Austria, Bahasa Jerman saya tumbuh lumayan pesat. Bangun tidur, wecker radio langsung menyapa dalam bahasa Jerman full. Dan saya tinggal di asrama yang isinya tidak ada orang Indonesia lain. Dan waktu itu internet juga belum ada, sehingga kita benar-benar dipaksa berkomunikasi hanya dengan bahasa Jerman. Bahkan saya mencoba menulis buku harian dalam bahasa Jerman. Hasilnya, setelah dua tahun, saya bahkan bisa mimpi dalam bahasa Jerman !!!
Di tahun kedua saya memiliki tetangga yang mahasiswa doktorat dari Mesir dan Thailand, yang selalu berkomunikasi di antara mereka dalam bahasa Inggris. Akhirnya saya mulai belajar lagi berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Saya usahakan setiap jadwal masak & makan bersamaan dengan mereka, supaya bisa ngobrol dalam bahasa Inggris. Tetapi lucunya, kalau saya ragu-ragu, reflek saya adalah mencarinya kembali ke bahasa Jerman. Kamus yang saya pakai adalah kamus Jerman-Inggris. Belakangan, saya menulis thesis S2 saya dalam bahasa Jerman, tetapi disertasi S3 saya putuskan dalam bahasa Inggris – lebih agar mudah diakses orang dari seluruh dunia. Bahasa Jerman cuma digunakan oleh kurang lebih 120 juta orang; sedang bahasa Inggris oleh 750 juta orang. Di PBB, bahasa resmi dunia ada 6: Inggris – Perancis – Spanyol – Rusia – Arab – China.
Setelah bahasa Jerman saya mantap, serta terinspirasi oleh profesor kimia yang hobby bahasa tadi, saya mencoba belajar beberapa bahasa lainnya. Kebetulan di masjid khutbah disampaikan dalam bahasa Turki. Maka saya lalu belajar bahasa Turki. Wow, ternyata bahasa Turki lebih rumit dari bahasa Jerman. Kemudian saya sempat punya teman pena orang Belanda. Karena ada kedekatan bahasa Jerman dengan bahasa Belanda, saya sempat beberapa lama berkorespondensi dalam bahasa Belanda. Kemudian ketika tahun 1988 saya berkeliling Eropa, saya membawa kamus-kamus kecil untuk mempelajari bahasa-bahasa negeri yang saya lewati : Perancis – Italia – Spanyol – Yunani. Kalau cuma untuk little talk (sekedar bilang selamat pagi, mana arah ke …….. , berapa harganya, dll) ternyata memang tidak membutuhkan waktu yang lama. Tetapi belajar seperti ini ya cepat lupa lagi.
Di tahun ke-4 di Austria, saya iseng-iseng ikut kuliah bahasa Arab di Universitas Wina. Cuma 2 x 2 jam/minggu. Di sini ikut kuliah apa saja bebas, dan waktu itu tidak perlu bayar. Semula saya merasa paling hebat, karena dari seluruh mahasiswa, mungkin saya yang sudah hafal huruf Arab duluan. 🙂 Tetapi ternyata mind-set ini kurang baik. Ternyata pelajaran berjalan cepat. Dari awal, bahasa Arab diajarkan tanpa tanda harakat (syakal). Dari awal: arab gundul. Ujian Semester adalah potongan koran berbahasa Arab lalu pertanyaan-pertanyaan, yang juga dalam Arab gundul. Wow … nyerah dech … Sepertinya memang harus seserius atau bahkan lebih serius dari ketika saya belajar bahasa Jerman dulu.
Bahasa Arab adalah bahasa persatuan Islam dan konon akan menjadi bahasa di Surga. Tetapi saya yakin, orang yang dimasukkan Allah ke surga, pasti otomatis akan bisa berbahasa Arab, sekalipun di dunia satu hurufpun tak kenal, karena di surga itu segala keinginan akan terkabul. Sedang sebagai bahasa persatuan, bahasa Arab tidak perlu diperdebatkan lagi, karena sumber-sumber ilmu dan sejarah Islam semua dalam bahasa Arab. Tetapi memang tidak otomatis bisa bahasa Arab akan mengantarkan orang ke pemahaman Islam yang benar. Andaikata begitu, niscaya semua orang di Timur Tengah yang dari kecil lancar berbahasa Arab akan ber-Islam dengan benar. Faktanya kan tidak begitu. Oleh sebab itu, belajar bahasa Arab dan belajar Islam keduanya harus dilakukan. Belajar bahasa Arab agak sulit dengan “sambil lalu” – “sambil baca kitab di halaqah”, apalagi dengan musyrif yang bahasa Arabnya juga masih belum kokoh. Kalau seperti ini, hasilnya malah kemampuan bahasa Arab tidak dapat, dan materi halaqah juga tidak tertransfer dengan sempurna.
Kursus-kursus singkat yang ditawarkan (dari yang 6 minggu sampai 6 jam) tidak lain hanya memberi motivasi saja. Buat beberapa orang, motivasi ini dapat menjadi cambuk mereka belajar selanjutnya, baik mandiri atau dengan komunitasnya. Percaya diri berbahasa asing itu tidak perlu menunggu fasih berbahasa asing. Tetapi walau baru little-talk (lebih rendah dari small-talk), percaya diri ini sangat perlu. Kalau sudah tidak percaya diri, maka bahasa yang telah dipelajari tidak akan pernah dipraktekkan, padahal kemampuan bahasa itu tumbuh seiring dengan praktek.
Hal ini ternyata tidak cuma untuk bahasa manusia. Bahasa komputerpun demikian. Setelah saya percaya diri dengan bahasa Pascal, saya lalu mulai lagi mempelajari bahasa Basic, Fortran, C, Lisp, Prolog, SQL, APL, dll. Intinya: belajar bahasa itu mesti serius sampai mencapai ambang kritis, pertama ambang “percaya diri bicara bahasa itu” – dan setelah itu jangan berhenti, teruslah belajar sampai “ambang bisa mimpi dalam bahasa itu” 🙂
Diagnosis Kemunduran Umat
Saturday, December 29th, 2012Prof. Dr. Fahmi Amhar
“Seorang dokter yang salah diagnosa, akan salah pula memberi therapi.
Bila ummat Islam salah memahami proses kemundurannya, maka mereka
akan salah pula dalam mencari cara-cara menuju kebangkitannya”
 Kalau kita mencoba melakukan analisis atas kualitas suatu ummat, tak terkecuali ummat Islam, maka kita harus menetapkan dulu tolok ukurnya, agar tak salah bila kita katakan suatu ummat itu maju atau mundur, dan bila mundur, kita juga tahu bagaimana seharusnya, atau ke mana langkah menuju.
Kalau kita mencoba melakukan analisis atas kualitas suatu ummat, tak terkecuali ummat Islam, maka kita harus menetapkan dulu tolok ukurnya, agar tak salah bila kita katakan suatu ummat itu maju atau mundur, dan bila mundur, kita juga tahu bagaimana seharusnya, atau ke mana langkah menuju.
Qualitas ummat terbaik adalah ditemui pada generasi Nabi, generasi sesudahnya (Tabiin) dan generasi sesudahnya lagi (Tabiit-Tabiin). (HR Bukhari, dll).
Qualitas itu diukur dengan kriteria yang uniq, yakni pada aktivitasnya dalam menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar (QS 3:110). Tugas ini memerlukan type-type manusia muttaqin, mereka yang hanya takut kepada Allah saja, dan tidak bisa dipungkiri, bahwa jumlah “muttaqin per kapita” yang terbanyak adalah di zaman Nabi.
Di zaman sesudahnya, jumlah ini makin menurun secara berangsur-angsur, meskipun wilayah Islam dan populasi muslim terus membesar, dan karya-karya peradaban baik dalam ilmu-ilmu agama maupun dalam iptek dan kesenian terasa menuju “masa keemasan”-nya. Dalam konteks materialisme seperti pada budaya Barat, memang qualitas suatu bangsa biasa diukur dari produk peradaban (iptek, kesenian, arsitektur, etc). Namun dalam konteks Islam, ukuran yang standard adalah kontribusi bangsa itu dalam amar ma’ruf nahi munkar. Jadi peradaban sesungguhnya hanyalah alat semata. Motivasi amar ma’ruf nahi munkar-lah yang pernah membawa ummat Islam untuk menciptakan peradaban yang maju, karena berlaku prinsip: “APA YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI YANG FARDH, HUKUMNYA JUGA FARDH”.
Bila kita analisis, maka proses kemunduran ummat Islam itu secara singkat bisa dibagi dalam tiga tahapan:
1. Kekaburan Fikrah Islamiyah (=ide atau fikiran)
2. Kekaburan Thariqah Islamiyah (=methode mewujudkan ide)
3. Kekaburan Relasi antara Fikrah dan Thariqah.
1 Kekaburan Fikrah Islamiyah
1.1 Merebaknya Mitos
Kekaburan fikrah mulai terjadi sejak dini (abad 2 H), saat derap perluasan wilayah Islam kurang terimbangi dengan derap pewarisan fikrah Islam. Akibatnya, berbagai bangsa yang tadinya hidup dalam mitos dan filsafat serta mistik Yunani/Mesir, Persia atau India, tidak segera membuang mitos/filsafat/mistik itu dari alam fikirnya, melainkan mencoba “mengawinkannya dengan Islam” atau dengan kata lain: “mengislamkan mitos” dan “memitoskan Islam”.
Contoh dari mitos ini banyak sekali. Kita tahu, dalam semua ajaran lain, keyakinan dasarnya selalu berasal dari mitos, atau suatu aksioma dasar yang tidak bisa dilacak secara rasional. Bangsa yang tadinya penganut mitos itu, ketika beralih ke Islam, pun memandang aqidah Islam sebagai mitos. Person Rasul berubah dari sosok manusia yang bisa ditiru setiap muslim (sebagai uswatun hasanah) menjadi sosok keramat yang supranatural. Bahkan belakangan, seorang ‘alim yang aslinya hanyalah ilmuwan atau pakar, yang dalam ijtihadnya bisa benar maupun salah, tiba-tiba dipandang sebagai “orang suci” yang tidak mungkin salah, sebagaimana orang-orang Kristen memandang Paus, atau orang-orang Hindu memandang Sri Bhagawan.
Ketika seseorang bisa menjadi “kult-figur” karena mitos, maka orang-orang yang ada penyakit di hatinya berlomba untuk juga memiliki posisi di sana. Mereka melegitimasi diri di depan orang-orang yang tidak tahu dengan ayat-ayat Qur’an yang diselewengkan tafsirnya, atau dengan hadits-hadits yang dhaif atau palsu. Maka muncullah bid’ah di mana-mana.
1.2 Pengabaian Bahasa Arab
Kekaburan fikrah ini makin dipercepat tatkala bahasa Arab tidak lagi dipelihara. Hingga berakhirnya masa khilafah Abbasiyah, islamisasi selalu dilakukan bersama-sama dengan “arabisasi”. Dengan itulah, maka orang-orang yang berpotensi dari seluruh dunia Islam, meskipun berasal dari etnis bukan Arab, bisa memberikan kontribusinya yang besar pada Islam. Bahasa Arab klasik sebagai bahasa Qur’an, yang memang paling kaya di antara bahasa-bahasa di dunia, menjadi bahasa internasional, bahasa silaturahmi ummat Islam, dan bahasa ilmu pengetahuan Islam. Tak ada suatu kata yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa Arab.
Adalah keputusan yang fatal dari suatu masa khilafah Utsmaniyah, ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan tradisi tersebut, dengan alasan, agar Islam lebih mudah “diserap” tanpa barier bahasa Arab. Namun akibatnya, di negeri-negeri yang belum berbahasa Arab, bahasa Arab menjadi “hak istimewa” selapis kecil kaum terpelajar saja, sedangkan bagi ummat, khasanah ilmu yang luar biasa, yang selama itu hanya ada dalam bahasa Arab, menjadi tertutup.
1.3 Surutnya Ijtihad
Akibatnya, ketika faktor bahasa Arab menjadi barier, maka ijtihad tidak lagi dikerjakan dengan cukup. Padahal ummat Islam hanya bisa terus menerus menghadapi zaman, bila mereka terus menerus berijtihad. Sedangkan ijtihad hanya bisa dikerjakan dalam bahasa Arab klasik. Ketika sebagian orang nekad berijtihad tanpa bekal yang memadai, timbullah berbagai “fatwa nyleneh”, sehingga beberapa penguasa pada zaman itu merasa perlu untuk “menutup pintu ijtihad”. Suatu keputusan berniat baik namun gegabah dan justru memperburuk suasana.
Karena ijtihad tidak lagi dikerjakan, maka persoalan baru tampak menjadi muskil dipecahkan dengan Islam. Maka ummat Islam pun mulai mengambil solusi dari luar Islam. Mulai abad 17 (abad 11 H) sejalan dengan invasi Barat ke negeri-negeri muslim, ummat Islam mengambil sistem ekonomi kapitalis dan sistem hukum & politik sekuler, meskipun mereka masih “menguji” agar “tidak bertentangan dengan Islam”. Namun kekaburan ini sudah terlanjur menjadi, dan ummat Islam tidak lagi kritis, bahwa sistem asing yang diimpornya itu didasarkan pada mitos. Bahkan lambat laun mereka cukup fanatik pada sistem asing itu, karena telah ada seseorang yang juga sudah dimitoskan yang melegitimasinya.
2 Kekaburan Thariqah Islamiyah
Islam bukanlah ajaran yang memberikan sekedar ide, melainkan juga menunjukkan metode untuk mewujudkan ide tersebut, yang dikenal dengan term “thariqah”. Bila kita selidiki, semua perintah-perintah ilahi selalu termasuk fikrah (=ide) atau thariqah (=metode), dan tak ada perintah fikrah tanpa thariqah, atau thariqah tanpa fikrah.
Sebagai contoh, “Berimanlah” adalah perintah fikrah. Perintah thariqah yang berkaitan dengan ini adalah hal-hal yang menyangkut mengamati alam serta melakukan pemikiran rasional yang menjadi landasan iman, dan perlindungan iman termasuk jihad serta hukuman mati bagi orang-orang yang murtad.
Contoh lain, “Jiwamu, Hartamu dan Kehormatanmu adalah suci” adalah perintah fikrah. Perintah thariqah yang berkaitan adalah perlindungan atas kesucian itu, seperti fasilitas kesehatan, polisi, pengawas pasar, peradilan keluarga, dan juga termasuk hukuman bagi pelanggaran atas tindak pidana yang terkait.
Kekaburan atas thariqah Islamiyah bisa dibagi dalam tiga tahap:
2.1 Kendurnya Jihad
Pada awalnya ummat Islam sadar bahwa hidup mereka dipersembahkan untuk Islam serta untuk memanggul dakwah Islam, dan ini berarti termasuk jihad al-qital (perang fisabilillah), agar tak ada lagi fitnah di muka bumi sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka (QS 2:193).
Dan karena jihad memerlukan persiapan yang matang, maka otomatis kaum muslimin menyiapkan tubuh yang sehat dan kuat, keluarga yang intakt, negara yang adil, ekonomi yang mapan, IPTEK yang maju dan ibadah yang khusyu’. Jihad sebagai alat dakwah sekaligus menjaga kaum muslimin agar selalu menjadi ummat terbaik di muka bumi (khairu ummat) agar ummat lain yakin, bahwa ajakan kepada Islam memang akan membawa mereka menjadi maju, adil, makmur dan diridhoi Allah. Bila mereka perlu contoh, maka silakan melihat sendiri fakta di Daarul Islam. Saat itu, adakah negara yang lebih baik dari Daarul Islam? Inilah dakwah yang sangat meyakinkan.
Namun lambat laun, bersamaan dengan kekaburan fikrah, maka orientasi ummat Islam mulai bergeser. Di satu sisi, sebagian ummat lebih cenderung untuk “meresapi kehidupan religi” yang disalahtafsirkan sebagai “Jihad Qubra”, sebagaimana tampak dalam ribuan sekte-sekte “sufi” yang menjauhi jihad serta amar ma’ruf nahi munkar. Di sisi lain, sebagian ummat lebih cenderung “menikmati rejeki Allah” dengan hidup lux, walaupun dari rejeki yang halal. Yang jelas, jihad mulai redup. Dan dakwah mulai dikerjakan “sambil lalu”. Ini yang menjelaskan, mengapa dakwah ke Asia Tenggara praktis tanpa jihad, walau tetap pantas dikagumi, bahwa “dakwah sambil lalu” dari para pedagang itu toh masih memiliki kemampuan yang tinggi untuk mendesak suatu ajaran lama. Namun fikrah yang masuk sudah tidak sejernih dakwah pada generasi awal Islam.
2.2 Lenyapnya Daulah Khilafah
Ketika qualitas ummat semakin redup, maka semakin turun pulalah kontrol atas kekuasaan sesuai pepatah Arab (“Pemimpinmu itu sebagaimana kamu”). Daulah khilafah, meski saat itu masih ada dan diakui ummat Islam di seluruh dunia, namun kekuasannya mulai terbatas sekedar sebagai simbol persatuan spiritual, sedangkan di mana-mana mulai tampil raja-raja monarki, yang meskipun masih memerintah dengan Islam, namun tak lagi sepenuhnya menyemangatkan “Jama’atul Islamiyah” (=negara dunia Islam) melainkan “Jama’atul Qaumiyah” (=negara kebangsaan). Akibatnya, potensi ummat Islam mulai tidak menyatu menjadi sinergi yang luar biasa. “Take care” ummat Islam di suatu wilayah atas penderitaan ummat Islam di wilayah lain tinggal sebatas pada doa dan sedekah yang tidak seberapa, karena khilafah tidak lagi kuat untuk menjalankan fungsi baik komando maupun koordinasinya. Di samping itu, bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu mulai kurang dipahami oleh ummat Islam sendiri, karena kurang dipelihara.
2.3 Lepasnya Bumi Islam
Ketika khilafah mulai lemah, sementara fikrah sudah sangat kabur, maka relatif mudah bagi bangsa Barat untuk invasi dengan menggunakan politik devide et impera. Antar raja-raja muslim karena semangat qaumiyahnya mulai gampang dihasut dan diadu domba. Maka Barat menjanjikan bantuan pada salah satu pihak, dengan imbalan wilayah. Para penguasa muslim tidak lagi sadar, bahwa adalah haram hukumnya meminta perlindungan pada orang-orang kafir, dan perselisihan antar kaum muslimin harus dicarikan penengah yakni dari khalifah. Namun apa daya ketika khilafah sendiri mulai lemah?
Maka satu demi satu bumi Islam mulai lepas ke tangan penjajah. Dan mulailah, sedikit demi sedikit penjajah memasukkan sistem kufur dalam kehidupan, dan menggeser sistem Islam. Proses ini makin dipercepat ketika kalangan elit muslim juga terpengaruh fikrahnya, apalagi melihat Barat secara material/fisik berada di atas angin.
Ketika di abad-20 bumi Islam diberi kemerdekaan kembali – karena desakan politik (pseudo) anti imperialisme dari Uni Soviet maupun Amerika Serikat, sehingga kolonialisme gaya lama menjadi tidak “in” lagi, sistem yang berlaku pada mereka, serta fikrah yang lazim pada mereka, sudah sangat terkontaminasi dengan produk-produk mitos Barat. Sementara khilafah, sebagai simbol persatuan ummat Islam, pun sejak 1924 secara formal sudah tidak ada lagi.
3 Kekaburan Relasi Fikrah-Thariqah
Bila di kesempatan yang lalu kita sama-sama melihat secara terpisah bahwa bidang fikrah maupun thariqah sama-sama terserang “penyakit”, maka lepasnya kaitan antara fikrah dan thariqah lebih mempercepat lagi proses tersebut, atau setidaknya, menyulitkan proses penyembuhannya. Ibarat seorang pasien penyakit jiwa yang juga mengalami penyakit jasmani, maka mestinya penanganannya dilakukan secara holistis (“menyeluruh”), dan tidak sepotong-sepotong, karena kestabilan jiwa juga tergantung pada kesehatan jasmani, dan demikian pula sebaliknya.
3.1 Disintegrasi Studi Islam
Pada awalnya, kaum muslimin mempelajari Islam secara menyeluruh. Prioritas mempelajari ilmu tidak tergantung dari subyeknya, namun semata dari hukm syar’i amal/prakteknya (fardh-mustahab-mubah). Suatu amalan yang fardh, maka semua ilmu yang terkait pun fardh. Maka ketika jihad fardh, iptek pendukung jihad pun fardh. Demikianlah, ketika studi Islam dikerjakan dengan benar, tak ada dikotomi antara so called “ilmu agama” dengan “ilmu dunia”, tidak ada pemisahan antara hukum waris dengan aljabar, atau ilmu sholat dengan astronomi, dll.
Namun lambat laun, sejalan dengan merebaknya mitos dan melemahnya ijtihad, kaum muslimin lebih berkonsentrasi pada ilmu-ilmu “ide” namun mengabaikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan metode pelaksanaan ide-ide tersebut. Maka mereka memusatkan diri pada peraturan ibadat ritual (sholat/puasa) atau tentang nikah dan cerai; namun mengabaikan misalnya peraturan tentang jihad, khilafat, lembaga peradilan dan sistem ekonomi Islam. Belakangan, sistem peradilan bahkan dipisah menjadi peradilan sistem (al-qadhi an-Nizhami) yang menjalankan hukum positif (non Islam) yang berkaitan dengan pidana, ekonomi, tata negara dsb; dan peradilan agama (al-qadhi as-Syar’i) yang cuma mengurusi keluarga (nikah, cerai, waris). Hukum Islam tidak lagi dijadikan pegangan untuk semua jenis peradilan.
Mereka mempelajari Islam berlawanan dengan metode yang diperlukannya. Sebelumnya, fiqh selalu dipelajari secara praktis, yang sesuai masalahnya akan dijalankan oleh individu, keluarga atau negara sebagai organ exekutif. Pada awalnya, fiqh berkembang di tangan para mujtahid yang diikuti oleh qadhi (=hakim), sehingga masalah yang dibahasnya selalu relevan dengan realita. Maka ketika syari’ah tidak lagi dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum positif, mulailah ia jauh dari realita. Fiqh Islam didegradasi menjadi aspek teoretis-moral saja. Ia tidak lagi menjadi alat untuk memberikan solusi bagi permasalahan sehari-hari ummat, dan para ahlinya diturunkan jabatannya menjadi sekedar penceramah atau missionaris yang membosankan masyarakat dengan khutbahnya yang selalu diulang-ulang, tanpa bisa melahirkan suatu energi yang produktif. Ujung-ujungnya, studi Islam dianggap “melangit” dan tidak “membumi”.
Akibatnya, pemuda-pemuda yang cerdas dari ummat Islam pada umumnya akan lebih condong pada studi yang lebih praktis seperti teknologi, kedokteran, ataupun “ilmu-ilmu sistem” yang dipakai, seperti ekonomi atau hukum positif, meskipun tidak berasal dari Islam. Dan sebaliknya, studi Islam tinggal ditekuni oleh mereka yang secara umum “second class”, walaupun tetap ada satu dua orang yang gemilang, sebagai perkecualian. Sementara itu, secara keseluruhan, ummat menganggap studi Islam sebagai fardhu kifayah, dan gugurlah kewajiban mereka bila telah ada orang yang mengerjakannya. Padahal mestinya, setiap muslim yang dewasa dan berakal sehat, fardhu ain untuk mengetahui segenap peraturan Islam yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari, karena ia diwajibkan untuk senantiasa beriorientasi pada perintah dan larangan Allah. Hanya ijtihad untuk menurunkan hukm syar’i dari Qur’an dan Sunnah yang fardhu kifayah.
Akibatnya, sprial kemunduran studi Islam makin menjadi-jadi. Mereka yang akhirnya secara formal dianggap “pakar” dalam studi Islam, sering tidak lagi kompeten untuk mengajukan Islam sebagai solusi permasalahan aktual. Bahkan tidak jarang, orang yang hanya mengenal Islam sepotong-sepotong, dengan mudah dijadikan masyarakat sebagai “tokoh Islam”, yang didengar ucapannya, dan diikuti pendapatnya.
3.2 Evolusi Islam
Akibat “the wrong man on the wrong place” ini, yang sering ada bukannya “Islam meluruskan masyarakat” namun “Islam disesuaikan dengan masyarakat”. Karena ummat tidak mengetahui lagi metode menjalankan ide-ide asli Islam, maka Islam dicoba ditafsirkan kembali agar konform dengan “semangat zaman”. Yang dimasuki tidak cuma aspek-aspek hukum parsial, namun bahkan ushul fiqh yang fundamental. Maka timbullah prinsip-prinsip nyeleneh seperti “Fiqh itu mengikuti tempat dan waktu”, atau “Tradisi itu boleh menjadi sumber hukum”, atau “Hukum boleh dihapus demi kemaslahatan”, dsb. Bahkan tidak jarang, mimpi ataupun contoh kehidupan / pengalaman pribadi seorang tokoh muslim kontemporer dijadikan hujjah.
Mereka mulai menghalalkan bunga dengan alasan itu perlu untuk uang yang mengalami inflasi atau untuk mengisi kas anak yatim (=ada maslahat). Pelacuran, judi atau konsumsi khamr mulai tidak dijauhi habis-habisan namun justru ditolerir secara terbatas dengan istilah “lokalisasi”. Kerjasama dengan negara perampok (Israel) dikatakan halal dengan alasan tidak ada mimpi yang melarangnya. Dan muslimah difatwakan tidak usah berjilbab karena istri sang tokoh juga tidak berjilbab.
Dan karena “semangat zaman”, maka semua hukum Islam yang lain pun disesuaikan agar cocok dengan ideologi modern, entah itu kapitalisme, marxisme, sekulerisme/demokrasi, dsb. Bahkan mereka menganggap “ada demokrasi dalam Islam” atau “ada kapitalisme dalam Islam”. Mereka tidak lagi mampu melihat mitos-mitos yang ada di balik isme-isme modern itu, sehingga menganggap asas musyawarah sebagai demokrasi, pasar bebas sebagai kapitalisme, dan toleransi mazhab sebagai sekularisme.
Bahkan mereka anggap, syi’ar Islam bisa “ditinggikan” atau “disempurnakan” dengan slogan-slogan nasionalisme, demokrasi, hak asasi manusia, dsb. Mereka berpikir, dengan itu, Islam bisa ditampilkan dengan wajah yang lebih “ramah”. Namun pada hakekatnya, Islam justru semakin jauh dari kehidupan. Andaipun nama Islam tampil, ia tak lebih sekedar sebagai “agama yang diakui negara”, “agama negara” atau sekedar kenyataan bahwa “kekuasaan ada di tangan mereka yang mengaku muslim”. Dan ummat umumnya tanpa sadar sudah puas, bahwa kini mereka tidak lagi diperhamba oleh penjajah kafir, namun oleh “penjajah muslim”. Maka mereka menghentikan usaha untuk hanya diperhamba oleh Allah atau oleh hukum-hukum Allah saja.
3.3 Terpojok di Sudut Defensif
Ketika fikrah Islam sudah sangat redup, mitos sudah merajalela, orang menjadi mukmin tidak karena berpikir tetapi karena ikut-ikutan lingkungan, khilafah sebagai methode menerapkan Islam di masyarakat tidak exist lagi, bahkan masyarakat semakin asing dari ajaran Islam yang murni karena studi Islam ditangani oleh orang-orang yang bukan ahlinya, yang tidak meluruskan masyarakat namun justru merubah Islam, di saat yang sama datang serangan yang telak dari orang-orang kafir: MENYUDUTKAN ISLAM.
Musuh-musuh Islam sadar, bahwa tidak mungkin menghancurkan Islam dan ummat Islam dengan kekuatan senjata. Karena itu, mereka berupaya terus menerus tanpa henti, untuk minimal membuat Islam dan ummat Islam tidak lagi berbahaya bagi kepentingan mereka. Andaikata ummat Islam masih tegar seperti pohon yang sehat dan berakar dalam, maka niscaya badai topan sebesar apapun akan dengan tatag dihadapinya. Namun kini, ketika akar sang pohon sudah lapuk, maka terpaan angin sepoi-sepoi saja bisa membuatnya rubuh.
Maka ummat Islam dewasa ini umumnya kelimpungan, ketika dikonfrontasikan dengan berbagai ajaran Islam yang ada dalam Qur’an atau Sunnah sendiri. Mereka tidak bisa menerangkan, mengapa Islam memerintahkan memotong tangan pencuri, atau membagi warisan bagi lelaki 2x wanita, atau bahwa seorang lelaki boleh menikahi sampai 4 istri, atau bahwa dalam Islam ada perintah jihad, dsb. Ketika orang-orang kafir mengkritik hal itu sebagai barbarik, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, atau Islam itu fanatik dan agresif, ummat Islam umumnya hanya bisa dengan terbata-bata membela diri. Mereka mencoba menafsirkan kembali Islam, sekedar musuh-musuhnya puas, dan kritikan mereda.
Mereka katakan, perintah memotong tangan pencuri itu hanya metaforis. Mereka katakan juga, bahwa sekarang ini warisan harus dibagi sama, karena wanita muslim sekarang sudah sama derajatnya. Tentang polygami, mereka katakan, sebenarnya di Qur’an diharamkan, karena manusia tidak mungkin berlaku adil. Dan tentang jihad, mereka katakan jihad itu hanya dilakukan bila ummat Islam diserang (defensif).
Amboi, betapa jauhnya tafsiran-tafsiran “modern” ini dengan ajaran Islam yang murni. Karena dalam Sunnah-nya, Rasulullah telah menunjukkan sendiri bahwa ia memotong tangan pencuri, bahwa ia menikahi banyak istri, dan bahwa jihad yang dilakukan ummat Islam melawan Persia atau Romawi, sama sekali bukan jihad ketika ummat Islam diserang. Dan ajaran Islam merupakan risalah terakhir yang diturunkan Allah di muka bumi, sehingga tetap berlaku hingga hari kiamat. Maka betapa anehnya tafsiran-tafsiran baru, yang mungkin dilakukan dengan “niat baik”, namun hasilnya malah justru memporak-porandakan ajaran Islam yang murni. Kesalahan tafsir yang fatal ini terjadi, karena ummat Islam memisahkan antara fikrah dan thariqah, karena semua hukum yang dihujjat tadi, memang tak bisa jalan sendiri-sendiri, melainkan hanya berfungsi dalam rangkaian metode yang tepat, dalam suatu negara yang islami, dalam suatu daulah khilafah.
Spiral kemunduran berputar semakin cepat. Orang-orang yang ditokohkan berlomba mencari pembenaran atas perilakunya, sehingga banyak rakyat jelata yang karena kebingungan akhirnya memutuskan untuk beramai-ramai melepaskan kepercayaannya pada para ulama – termasuk ulama yang shaleh. Bahkan mereka yang semula gembira dengan type ulama ini, karena merasa bisa “ngerti bahasanya”, lambat laun akan dihadapkan dengan sejumlah besar kontradiksi. Dan akhirnya sama saja: makin jauh dengan ulama.
Ummat yang masih tersisa ghirahnya pada Islam mencoba langsung mempelajari Islam dari sumbernya: Qur’an dan Sunnah. Namun mereka lupa, bahwa untuk itu diperlukan seperangkat bekal, baik ilmu bahasa Quran (bahasa Arab klasik) maupun ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Karena mereka maju tanpa bekal ini, mereka akan terbentur ke sana ke mari. Akhirnya kalau tidak terjerumus ke extremitas yang satu (menganggap yang hukum Islam itu cuma fardh semua dan yang lain haram semua), akan terpuruk ke extremitas lainnya (menolak memakai hadits, karena terlalu was-was dengan hadits yang “tidak jelas”, dan ujung-ujungnya meragukan Qur’an, karena tanpa penjelasan dari hadits, Qur’an mustahil dipahami dengan benar).
Maka tak heran, ummat Islam sekarang hanya sensitif bila sisa-sisa rasa agamanya diganggu. Mereka menjadi bersikap menunggu (re-aktif) dan tidak berani memulai (pro-aktif). Mereka justru menghindari untuk dikenal sebagai muslim, karena ini berarti harus menghadapi berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Dan di masyarakat di mana muslim mayoritas, mereka hanya sensitif bila ada kristenisasi, namun “cuek” bila hukum-hukum kafir diberlakukan di atasnya. Bahkan mereka marah, bila ada orang yang berbeda madzhab sholat agak lain dengan mereka (misalnya tidak baca qunut), namun tenang-tenang saja, ketika harus bermuamalah dengan riba, atau harus mendidik anak dengan pola pendidikan dan kurikulum sekuler.
Ummat Islam jadi tersudut di pojok defensif. Jarang dari mereka yang berani mengambil inisiatif untuk menelanjangi berbagai ideologi kafir yang didasarkan pada mitos, entah mitos demokrasi (dalam politik), mitos pertumbuhan (dalam ekonomi), maupun mitos HAM (dalam sosial). Tidak ada lagi dakwah offensif sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dan para pengikutnya terdahulu.
Hasilnya memang tepat seperti yang diinginkan musuh-musuh Islam.
Islam kini tinggal ahlaq – tanpa jihad,
Islam kini tinggal ibadah (ritual) – tanpa syari’ah,
Islam kini boleh menyinari rumah, tapi bukan pasar, pabrik atau bank,
Islam kini boleh menguasai masjid, tapi tidak menguasai kantor,
Islam kini boleh bicara tentang akherat, tapi tidak tentang negara,
Islam yang boleh disanjung adalah Islamnya para pertapa shufi, dan bukan Islamnya umara’ yang zuhud, ulama faqih yang zuhud, aghniya’ yang zuhud atau mujahidin yang zuhud.
Islam yang tidak mampu menolong ummatnya sendiri, baik di Bosnia, Palestina, Chechnya atau Sudan, apalagi menolong dunia dari disorientasi kehidupan, dari AIDS, dari kerusakan lingkungan, dari kesewenang-wenangan para kapitalis di era globalisasi.
dan Qur’an boleh didendangkan di MTQ, dan bukan di Pengadilan,
dan Qur’an boleh dibacakan pada orang mati, bukan pada orang hidup,
dan Qur’an boleh diajarkan di pesantren, dan bukan di universitas,
dan Qur’an boleh untuk menghitung pembagian zakat, namun bukan untuk membagi kekayaan alam dengan adil,
dsb.
Inilah, Islam semakin jauh dari kehidupan, dan Ummat Islam semakin mundur, meskipun kadang mereka merasa “ada kebangkitan”, ketika melihat masjid penuh, MTQ semarak, dan para pejabat berlomba naik haji. Namun mereka bingung, ketika ketidakadilan tetap saja langgeng, dan korupsi, kolusi serta manipulasi malah justru makin menjadi.
Ibarat orang yang sudah sakit parah, Ummat Islam tidak disembuhkan, tidak dioperasi atau dikasih antibiotik, namun hanya dikasih valium. “Valium Islam”.
Dan inilah realita yang sangat pahit. Adakah obatnya? Pasti, untuk setiap penyakit, Allah telah menyiapkan obatnya. Masalahnya hanya apakah kita cukup tekun berikhtiar serta belajar dari ayat-ayat baik kauni maupun qur’ani, sehingga penyelidikan kita akhirnya sampai ke sana.

 Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.
Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.
Bekerja di
Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.
Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.
Bekerja di