Beyond the Scientific Way
Membebaskan Belenggu Jaringan Islam Liberal (JIL )
Saturday, January 5th, 2013Fahmi Amhar, pengajar Pascasarjana Universitas Paramadina
JARINGAN Islam Liberal (JIL) adalah sebuah fenomena menarik di Indonesia karena dianggap mendobrak kemapanan dan kejumudan berpikir. Hal itu bisa dimengerti karena rata-rata aktivis JIL memiliki latar belakang Islam tradisional, yang berorientasi masalah ubudiyah dan tradisi yang dogmatis, yang praktis harus diikuti tanpa diskusi. Padahal, aturan-aturan itu sering tidak relevan dengan pembebasan umat Islam dari kemiskinan, kebodohan, ataupun penindasan.
Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam revivalis, yang ingin menyelamatkan umat dengan syariat sering bersikap simplistis, misalnya menekankan syariat sekadar kewajiban mengenakan jilbab pada muslimah, atau hukum-hukum hudud pada kasus pidana, namun mereka jarang memiliki konsep yang komprehensif dan rasional tentang mekanisme pembebasan manusia dari berbagai keterpurukannya. Bahkan, cita-cita memunculkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* terkadang
diwujudkan dengan cara-cara kekerasan, dan inilah *trade mark* Islam radikal yang menjadi salah satu pendorong sehingga JIL merasa perlu bersuara lebih lantang.
Dengan demikian, saya melihat JIL sebagai suatu antitesis atas latar belakang jumud dan alternatif radikal yang miskin konsep. Ini suatu hal yang bisa dimengerti, namun tidak boleh dibiarkan.
*JIL terbelenggu*
Saya setuju dengan pendapat Ulil bahwa Islam itu semacam organisme dan bukan monumen yang mati. Untuk itulah, realitas sejarah Islam di masa awal membuka pintu ijtihad yang membuat peradaban Islam berkembang pesat.
Namun, ‘paradigma organisme’ ini jangan menjadi belenggu baru bagi kita, bila kenyataannya memang ada yang tidak memberi kesempatan ijtihad, karena sudah begitu terang (*qath’i*). Andai paradigma organisme ini begitu
menonjol, Islam tidak akan tersisa lagi. Salat, puasa, atau haji bisa-bisa dianggap aktivitas mubazir yang tidak relevan dengan pembebasan manusia dari keterpurukannya.
Demikian juga dengan ‘paradigma nonliteral’. Sesungguhnya, teks-teks Islam (Quran dan hadis) memiliki makna literal dan makna *syar’i* (hukum).
Makna *syar’i* memang harus dipahami dalam konteks pelaksanaan syariat lain yang lebih luas, namun juga bisa lebih terbatas. Istilah salat, yang bermakna literal doa, memiliki makna *syar’i* aktivitas tertentu yang dimulai dari takbiratulihram dan diakhiri dengan salam. Justru JIL saya lihat lebih sering memakai makna literal untuk ditafsirkan sesuka hawa nafsunya.
Dalam kejumudannya, umat Islam di Indonesia memang sering melakukan suatu ritual yang sebenarnya hanya budaya, tanpa dasar syar’i. Namun, dalam masyarakat tradisional, hal-hal seperti itu (seperti memakai jubah), atau bahkan yang termasuk TBC (tahayul-bidah- churafat) , bisa disakralkan. Dan inilah (sesuai latar belakang JIL) yang pantas dikaji ulang. Namun, bukan hal-hal yang memang bukan tradisi, bahkan di Arab sendiri. Jilbab, misalnya, bukanlah tradisi Arab di masa Nabi. Kalau sekarang di sana menjadi semacam tradisi, apa salahnya kalau Islam yang dulu memulai tradisi itu?
Konsep Ulil tentang adanya ‘nilai-nilai universal’ yang mewajibkan umat
Islam tidak memandang dirinya terpisah dari umat manusia yang lain, seperti
nilai ‘kemanusiaan’ atau ‘keadilan’ pada tataran praktis akan menemui jalan
buntu. Manusia di mana pun memang diciptakan Tuhan untuk memiliki berbagai
sifat yang sama, misal suka diperlakukan adil. Namun, bagaimana adil itu
diciptakan ternyata tidak bisa berhenti pada dataran filosofis, namun harus
turun ke dataran yuridis, bahkan pada beberapa hal harus turun lagi ke
dataran aritmetis (misalnya pada pengenaan pajak progresif atau juga
pembagian warisan).
Karena itu, kalau Ulil usul untuk mengamendemen aturan yang membedakan
muslim dan nonmuslim (karena konon melanggar prinsip kesederajatan) ,
konsekuensinya mestinya salat id boleh diimami oleh nonmuslim, atau kalau
yang agak kurang ritual ya nonmuslim harus ikut bayar zakat.
Tentunya banyak hal-hal yang lalu menjadi absurd.
Cita-cita bahwa agama adalah urusan pribadi, sedangkan pengaturan kehidupan
publik sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat melalui proses demokrasi,
realitasnya justru sering dilanggar para penganjurnya sendiri, begitu Islam
yang keluar sebagai pemenang proses itu. Ketika jilbab dikenakan muslimah
profesional secara sukarela, yang mengemuka bukanlah kebebasan pribadi untuk
beragama, melainkan kecurigaan atas fundamentalisme, bahkan terorisme.
Bahwa Islam pada tataran praktis hanya akan terealisasi jika kekuatan
real-politis di masyarakat sepakat menerapkannya, ya. Kalau ini disebut
proses demokrasi, silakan. Namun, kalau pada tataran ide umat Islam
memperjuangkan agar syariat Islam yang diterapkan, apanya yang salah?
Bukankah ada kekuatan-kekuatan lain yang juga ingin menerapkan ide-ide yang
lain?
Tentang Rasul Muhammad SAW, memang benar kita tidak diwajibkan mengikuti
secara harafiah. Dalam kajian ushul fiqh kita tahu, ada perbuatan Rasul yang
jibilliyah (wajar sebagai manusia Arab abad VI M), misalnya makan kurma atau
pakai jubah. Orang kafir pun saat itu demikian. Ada juga perbuatan Rasul
yang khas untuk beliau, tak boleh diikuti umatnya, misalnya boleh berpuasa
tanpa berbuka, atau menikahi sampai sembilan istri. Namun, selebihnya adalah
dalil syar’i. Tentunya dalil ini ada yang sifatnya fardu, mustahab, atau
mubah. Tidak semua yang dikerjakan Rasul itu fardu. Di sinilah pentingnya
belajar ushul fiqh. Namun, Ulil menggeneralisasi, menganggap Islam yang
dibawa Rasul hanya *one among others*, salah satu jenis Islam di muka bumi.
Kalau begitu, Islam yang lain mencontoh siapa?
Memang kebenaran bukanlah milik satu golongan saja. Namun, peradaban ataupun
disiplin ilmu mana pun pasti memiliki suatu *frame*. Islam, tentu saja,
hanya layak dipahami atau ditafsirkan oleh orang yang percaya bahwa dia *
frame* yang sah untuk dijadikan pandangan hidup. Akan *absurd* mengikuti
penafsiran Quran dari nonmuslim yang tidak percaya bahwa Quran adalah wahyu
Ilahi, se*absurd* mengikuti pendapat tentang sains dari paranormal yang
tidak percaya sains.
Saya setuju bahwa misi Islam yang terpenting adalah menegakkan keadilan,
terutama di bidang politik dan ekonomi. Dan tentu ada syariat yang mengatur
masalah ini, dan itu memang bukan syariat jilbab, memelihara jenggot, atau
hal-hal *furu’iyah*, melainkan syariat yang mengatur masalah kepemilikan,
muamalah, sistem moneter, dan hubungan luar negeri.
Namun, kembali *absurd* ketika Ulil mengatakan upaya menegakkan syariat
adalah wujud ketidakberdayaan umat Islam atau mengajukan syariat Islam
adalah sebentuk kemalasan berpikir.
Memang kalau melihat ‘habitat’ Ulil dari kalangan tradisional yang jumud
atau menghadapi kalangan radikal yang miskin konsep, pemahamannya adalah
refleksi pengalamannya yang terbatas. Namun, generalisasinya tadi sungguh
tidak ilmiah.
Fakta, ada kelompok-kelompok yang berupaya menegakkan syariat namun bukan
sebagai wujud ketidakberdayaan ataupun malas berpikir. Gerakan Ikhwanul
Muslimin ataupun Hizbut Tahrir, misalnya, banyak menerbitkan buku-buku yang
memuat ide-ide tentang pengentasan kemiskinan (sistem ekonomi Islam) atau
mengatasi kezaliman (sebagai lawan ketidakadilan) secara syariat. Mereka
berjuang tanpa kekerasan.
Dan kalau Ulil keberatan dengan pandangan bahwa syariat adalah suatu ‘paket
lengkap’ untuk menyelesaikan masalah di dunia di segala zaman, selain
barangkali ini karena keterbatasan pemahaman Ulil atas syariat itu sendiri,
juga keterbatasan dia memahami apa itu ideologi.
Ideologi adalah suatu ide dasar yang di atasnya dibangun suatu paket lengkap
sistem untuk solusi problematik manusia.
Maka, kalau Ulil mengkritik orang-orang yang memahami Islam sebagai ideologi
yang mengajukan syariat sebagai paket lengkap solusi, mengapa dia tidak
melakukan kritik yang sama atas ideologi sekulerisme, yang juga mengajukan
paket solusi yang sama hanya atas dasar yang berbeda?
Sesungguhnya ide liberalisme JIL hanyalah salah satu unsur dalam paket
sekulerisme, yang unsur lainnya adalah demokrasi, kapitalisme, dan *last but
not least*: imperialisme. Di sinilah, saya katakan, kawan-kawan di JIL harus
melepaskan belenggu mereka dulu. Dalam bahasa ESQ perlu *zero mind
process*dulu. ***
Belajar Menjadi Guru, Dosen, Widyaiswara, Ustadz …
Friday, January 4th, 2013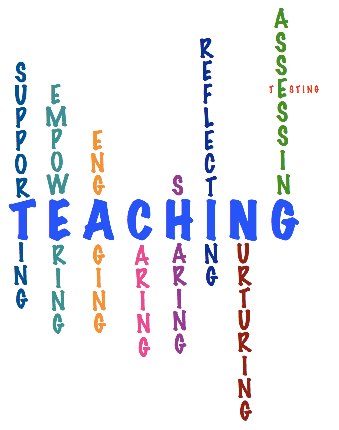 Siapakah guru dalam hidup Anda yang paling Anda kagumi?
Siapakah guru dalam hidup Anda yang paling Anda kagumi?
Apa yang sangat menginspirasi dari guru Anda itu?
Guru adalah salah satu profesi yang paling dikenal anak-anak. Sangat banyak anak punya cita-cita jadi guru, selain mungkin jadi dokter, insinyur atau pilot. Tetapi ketika mereka semakin besar, semakin kenal dengan kenyataan kehidupan guru, semakin sedikit yang masih mempertahankan cita-cita ini. Baru akhir-akhir ini saja, profesi guru “booming” lagi. Itu setelah di berbagai daerah, guru mendapat tunjangan profesi 1x gaji. Akibatnya, FKIP di berbagai kampus menjadi favorit, bahkan di beberapa kampus, persaingannya mengalahkan FT atau FE.
Sejujurnya, saya termasuk yang tidak pernah punya cita-cita jadi guru. Kalau jadi ilmuwan ya. Tetapi ternyata perjalanan hidup saya menyebabkan saya melewati fase menjadi guru, juga dosen, widyaiswara, dan bahkan ustadz 🙂 Walaupun semua mungkin pakai embel-embel “Luar Biasa”.
Saya pertama kali “pura-pura” jadi guru, itu kelas 2 SMP, ketika di sekolah, guru sejarah saya mencoba menerapkan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Anak-anak diminta membentuk kelompok @ 4 orang, lalu masing-masing diberi tugas suatu bab di buku paket, lalu “mengajar” siswa yang lain di depan kelas, bahkan sampai memberikan test. Tetapi seingat saya tidak semua kelompok sempat maju, karena waktu keburu habis. Saya beruntung termasuk yang sempat tampil, bahkan saya yang didaulat untuk yang berdiri mengajar di depan kelas.
Setelah itu ternyata saya jadi sering “mengajar” untuk berbagai hal yang lain. Mengajar PKS (Patroli Keamanan Sekolah), lebih tepatnya mungkin disebut Melatih. Sebelumnya saya dan beberapa kawan dilatih menjadi anggota PKS oleh Polres. Tugas PKS itu yang terpenting seperti Polantas, tetapi khusus untuk menyeberangkan anak-anak sekolah di depan sekolah. Maklum tenaga polisi saat itu dirasa terbatas. Setelah itu, beberapa kali seminggu, pagi pukul 6.30 kami sudah bertugas. Setelah praktek beberapa bulan, sekolah merasa perlu regenerasi, sehingga kami melatih adik-adik kelas.
Setelah PKS, pengalaman menjadi “guru” yang lebih panjang ada di Pramuka dan KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) di SMA. Walaupun kalau direnung-renungkan sekarang, banyak “pelajaran” di Pramuka saat itu yang “nggak mutu”, tapi dulu koq ya percaya diri saja ya … he he … Kalau KIR agak mending. Sampai sekarangpun saya kira masih banyak pelajaran yang relevan, bahkan tidak cuma untuk siswa SMA, bahkan untuk sarjana yang lagi meniti karier jadi peneliti muda 🙂
Sewaktu saya kuliah di Austria, saya juga punya pengalaman beberapa kali jadi “guru”. Pertama “guru” internet. Ini terjadi tahun 1995, sewaktu penggunaan internet masih relatif awal. Mungkin ini lebih tepat disebut “tutorial”. Kedua tahun 1996, “guru” bahasa Indonesia untuk orang asing. Ternyata rumit juga mengajar bahasa Indonesia yang sistematis untuk orang bule. Murid-murid saya saat itu ada 3 kelompok motivasi. Pertama yang motivasinya pekerjaan, yakni mereka akan dikirim bekerja di Indonesia (biasanya teknisi atau personil bisnis pariwisata). Kedua yang motivasinya travelling. Ada murid saya yang profesinya Profesor Fisika, tetapi hobby travelling, dan liburan mendatang ingin “blusukan” mengelilingi Indonesia. Alamak, waktu itu saya juga belum pernah keliling Indonesia. Yang lucu yang ketiga, motivasinya keluarga. Ada murid saya, wanita Austria yang akan menikahi pria Indonesia. Jadi dia perlu belajar banyak hal agar keluarganya harmonis.
Tahun 1997, sepulang dari Luar Negeri, beberapa saat lamanya saya diminta mengajar di sebuah kursus programming di suatu perusahaan. Mereka minta diajar programming dalam Visual Basic. Sejujurnya, saat saya meng-iyakan, saya belum pernah lihat Visual Basic. Saya memang punya pengalaman programming yang cukup panjang dalam C, Pascal, Fortran, Lisp, SQL dan Basic. Tetapi Visual Basic? Akhirnya saya praktis hanya menang 1 minggu dari peserta. Tetapi alhamdulillah dalam waktu singkat saya sudah lumayan expert. Repotnya ketika di akhir kursus, ada peserta yang tanya, apakah saya sudah punya “Microsoft Certified Programmer” ? Saya menjawab diplomatis, “Sepertinya Bill Gates juga belum punya tuh? ” 🙂
Karena saya sudah mengantongi gelar Doktor, maka mulailah saya beranjak dari “guru kursus” ke dosen. Ada prodi S1 suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meminta saya masuk dalam tim dosennya. Teorinya, kalau saya masuk, ijazah S3 dan sejumlah publikasi saya bisa mendongkrak nilai akreditasi BAN-PT untuk prodi di PTS tersebut. Ternyata betul. Bahkan waktu itu, prodi di PTS tersebut terakreditasi lebih dulu dari PTN pembinanya !!! Tetapi setelah terakreditasi, tiba-tiba jumlah mahasiswa yang diterima PTS itu berlipat 3x. Dosennya yang kewalahan. Kalau cuma mengajar sih mungkin tidak terlalu berat. Tetapi kalau harus mengoreksi tugas, wow … capek dech … Apalagi mengajar di LCU (Low Cost University) ini harus lebih banyak ibadahnya … 🙂 Lima tahun kemudian, karena saya semakin sibuk di kantor, saya makin mengurangi jam mengajar saya di PTS tersebut, sampai akhirnya off sama sekali.
Saat itu saya juga mencoba menjadi dosen program S2 di IPB dan di UPM (Universitas Paramadina Mulya). Yang S2 di IPB ini program internasional, wajib pakai bahasa Inggris. Sedang yang di UPM kelas eksekutif, jadi kuliahnya malam. Sangat berbeda dengan S1, menjadi dosen S2 jauh lebih “santai”. Mahasiswanya tidak banyak, tetapi honornya banyak … he he … Kadang saya berpikir, jangan-jangan honor saya ngajar S2 ini sebenarnya untuk jerih payah ngajar S1 di LCU itu … 🙂 Yang jelas, ndosen di S2 bersama para eksekutif itu membuat kita jadi terus terasah. Kita mengakumulasi berbagai pengalaman dan wawasan.
Meski menjadi selingan yang menggairahkan, tetapi karena saya secara resmi bukan dosen, maka kadang-kadang tugas ini sedikit “terganggu”. Yang paling ringan adalah ketika tiba-tiba ada jadwal rapat yang berdekatan dengan jadwal mengajar. Kadang-kadang sulit kita mencari waktu pengganti. Yang lebih repot lagi adalah ketika kita punya atasan yang kurang suka atau bahkan tidak setuju kita “ndosen” pada jam kerja. Dianggapnya itu buang-buang waktu, atau bahkan “korupsi waktu”. Padahal sesungguhnya, pada saat mengajar, kita juga bertambah ilmu, dan juga memperluas jejaring, yang juga memiliki multiplier effect pada tugas-tugas kita di kantor. Mahasiswa S2 itu berasal dari berbagai daerah, berbagai lembaga, juga berbagai profesi dan latar belakang.
Ada beberapa kampus yang secara tersirat menawari saya pindah, jadi dosen full-time saja di sana. Mereka mengatakan, kalau jadi dosen full-time nanti bisa jadi Professor. Waktu itu saya coba hitung-hitung angka kredit kumulatif saya kalau dihitung sebagai dosen. Ternyata jauuuh. Terutama karena saya tidak bisa memenuhi porsi tri-darma perguruan tinggi yang pertama yaitu pendidikan/pengajaran. Ya maklum, ngajar di sana-sini cuma 2 SKS. Paling total cuma 6 SKS per semester … Kalau mau “ngebut”, mesti menulis buku ajar. Sebenarnya menulis buku ajar tidak terlalu susah, karena tidak harus penemuan sendiri. Bisa menggubah ulang apa yang pernah ditulis orang lain. Tetapi sepertinya saya nggak bisa menuliskan sesuatu yang tidak pernah saya dalami sendiri. Untunglah, kemudian muncul SKB Mendiknas-Kepala LIPI-Menpan yang mengesahkan adanya Profesor Riset, yakni jenjang Professor yang menjadikan riset sebagai komponen utama.
Selain itu, untuk berbagai diklat dari berbagai kementerian/lembaga saya juga diminta menjadi “Widyaiswara Luar Biasa”. Widyaiswara agak berbeda dengan dosen, karena yang dididik bukan mahasiswa (apalagi mahasiswa S1), tetapi orang dewasa yang kadang merasa sudah lebih berpengalaman, atau bahkan merasa “untuk apa harus ikut diklat lagi, toh sudah tua dan sebentar lagi pensiun”. Jadi perlu pendekatan yang berbeda, bahasa kerennya “Andragogi”, bukan “Pedagogi”. Di diklat yang diadakan Bakosurtanal/BIG, saya kadang menjadi WLB untuk bidang Pemetaan, Penegasan Batas, Penataan Ruang, Penanggulangan Bencana dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Di LIPI saya menjadi WLB Diklat Fungsional Peneliti tingkat Lanjut. Jadi WLB ini tidak terlalu stress, karena kita cukup banyak cerita dari pengalaman kita saja, dan gak usah bikin soal yang rumit seperti ujian mahasiswa. Biasanya sih – asal tidak keterlaluan – semua peserta diklat akan lulus. Toh terserah mereka, apakah ilmu yang kita berikan akan terpakai atau tidak pada lingkup pekerjaan mereka.
Yang terakhir setelah guru – dosen – widyaiswara, itu adalah ustadz. Ini seharusnya pos yang paling tinggi. Di Mesir itu, lulusan S1 syari’ah tidak langsung dipanggil Ustadz, tetapi “Mu’id”. Nanti kalau sudah S2, dia akan dipanggil “Musaid Mudaris”. Setelah S3 dipanggil “Mudaris”. Setelah mengajar dan riset kira-kira 5 tahun, akan dipanggil “Musaid Ustadz”. Baru setelah 10 tahun sejak S3, kalau angka kumnya tercapai dan senat setuju, akan dipanggil “Ustadz”. Jadi rupanya Ustadz itu sama dengan Professor. Tetapi di Indonesia, panggilan Ustadz bisa dicapai siapa saja. Sangat egaliter. Dan tahukah Anda, bahkan sejak saya masih SMP, saya sudah dipanggil “Ustadz” !!! Itu terjadi lantaran saya membantu mengajar membaca al-Qur’an belasan anak-anak kecil di masjid kampung. Kemudian menggantikan ayah saya yang wafat mengisi majlis taklim Ibu-ibu. Kemudian mengisi khutbah di sekolah. Tentu saja, sebagai “Ustadz” tingkah laku kita lalu juga jadi sorotan. Tapi ini bagi saya tidak masalah. Ketika saya pada usia 26 tahun sudah naik haji, tambah disorot lagi !!! Karena banyak orang yang menunda naik haji, karena takut nggak bisa “membuat dosa” lagi … Itu tanda orang yang kurang cerdas. Karena, kata Imam Ghazali, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati, dan kematian bisa datang kapan saja, tidak nunggu tua. Karena itu, ayo buruan jadi “Ustadz” — mumpung di Indonesia belum perlu syarat macam-macam seperti di Mesir – asal tahu diri saja kapasitas ilmunya … 🙂
Tapi fenomena “Ustadz TV” atau “Ustadz Google” akhir-akhir ini memang agak memprihatinkan. Seorang dianggap ustadz hanya oleh aktivitas ceramahnya, dan bahannyapun “cuma disedot dari Google”. Padahal aktivitas Ustadz – dan juga guru/dosen/widyaiswara pada umumnya – yang hakiki itu adalah MENGUBAH (CHANGE). Mengubah dari mindset (pola pikir), kemudian behaviour (perilaku), dari yang kurang cerdas menjadi cerdas, dari yang kurang cekatan menjadi cekatan, dan dari yang kurang islami menjadi islami – sesuai syari’ah. Percuma saja ngustadz di TV, ditonton jutaan orang, kalau tidak satupun yang berubah, karena isinya cuma banyolan. Lebih gawat lagi, kalau isinya memang mengubah, tetapi malah mengubah jadi makin tidak islami. Karena orang yang tersesatkan akan berkilah, “Lho ini kata Ustadz Fulan di TV hukumnya halal koq”. Padahal “fatwa halal” Ustadz Fulan itu ternyata cuma pakai “dalil perasaan”, kalau tidak “katanya” ya “pokoknya”.
Baik guru, dosen, widyaiswara maupun ustadz, semua memiliki tanggungjawab sampai akherat sana. Karena itu beruntunglah mereka yang memposisikan semua amal itu untuk ibadah, bukan sekedar untuk mencari penghidupan. Kita tidak usah risau dengan kompensasi yang kadang tidak sesuai dengan jerih payah, karena “Gusti Allah ora sare” (Tuhan tidak pernah tidur). Dia Yang Maha Adil tidak akan pernah membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Hal Jazaa’ul Ihsani Illal Ihsan”.
Salam.
Belajar dari Negeri Para Mullah
Wednesday, January 2nd, 2013Prof. Dr. Fahmi Amhar
“Pergi ke Iran mau ngapain? Mau jadi syi’ah?”, tanya seseorang. Pertanyaan tak serius ini tentu saja saya jawab dengan canda, “Lho saya kan sudah Ayatollah!”.
Ada juga canda yang lain, “Kalau belum menikah memang seharusnya ke Iran dulu, biar tidak menyesal …”. Konon sejak revolusi Islam, wanita Iran tidak boleh ikut seleksi wanita cantik sejagad seperti Miss Universe. Hal ini karena di Iran tidak ditemukan satupun wanita cantik. Adanya wanita amat cantik dan wanita cantik sekali …
Pertengahan tahun 2011, saya ke Iran diundang presentasi oleh International Conference on Sensors & Models of Photogrammetry & Remote Sensing di College of Engineering University of Teheran. Keputusan jadi berangkat diambil dua hari sebelumnya, setelah dipastikan kita bebas visa untuk seminggu. Meski jarang turis “nyasar” ke Iran karena berbagai travel warning dan citra Iran yang dibuat buruk media Barat, namun menurut saya ada dua hal yang perlu dipelajari dari negeri para Mullah ini. Pertama, tentang dunia sains di Iran yang tetap maju ditengah-tengah kesulitan akibat embargo yang dijatuhkan dunia. Kedua, realitas kehidupan sehari-hari di sebuah Republik Islam.

Tentang dunia sains di Iran:
Iran beruntung memiliki warisan kejayaan Islam masa lalu, bahkan juga dari masa pra Islam. Ingat, Salman al Farisi RA adalah sudah insinyur ketika dia masuk Islam. Nama-nama intelektual besar Islam seperti al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan Umar Khayam, “hadir” dalam kehidupan sehari-hari. Banyak jalan atau lapangan dinamai dengan tokoh-tokoh itu. Iran bahkan memberi penghargaan tahunan “Al-Khawarizmi Award” bagi ilmuwan muslim dunia yang dianggap berprestasi dalam inovasi teknologi. Setiap tahun mereka juga mengundang seluruh negeri Islam dalam sebuah pameran internasional sains dan teknologi.
Dalam conference ini, saya melihat bahwa kualitasnya masih di atas rata-rata conference sejenis yang diadakan di Indonesia. Tidak cuma bahwa sebuah konferensi ilmiah internasional diawali dengan pembacaan al-Qur’an, tetapi presentasi para peneliti Iran, termasuk yang masih mahasiswa benar-benar mengambil thema yang tidak mudah, meski banyak batasan yang mereka alami. Sebagai contoh, ada ilmuwan Iran yang membuat sebuah alat yang dicangkokkan pada sebuah alat yang lebih besar buatan perusahaan Austria, Vexcel, untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Tiba-tiba Vexcel dibeli Microsoft. Maka kerjasama dengan Vexcel otomatis batal, karena bila diteruskan, Microsoft akan kena UU Embargo. Dalam UU itu, semua perusahaan Amerika yang berhubungan dengan Iran akan dihukum. Kini Iran mencoba bekerja sama dengan China untuk alat yang serupa.
Namun kesulitan itu makin membuat Iran tertantang. Kata beberapa teknisi PTDI yang diperbantukan di industri pesawat Iran, mereka benar-benar “diperas ilmunya” selama di Iran. Ini sikap yang sangat berbeda dengan kita di Indonesia terhadap expatriat. Tak heran, nyaris tanpa pertolongan negara lain, tahun 2009 mereka sudah berhasil membuat roket yang dapat membawa satelit komunikasi ke orbit. Kalau Iran berhasil membuat bom atom, maka dengan roket tersebut Iran pasti akan dapat menjatuhkan bom ke mana pun di seluruh dunia. Oleh karena itulah, Amerika dan sekutunya makin kencang dalam membatasi gerak gerik Iran. Hal yang sejenis barangkali akan terjadi ketika Khilafah, yang mungkin jauh lebih “berbahaya” bagi Barat daripada Iran, diproklamasikan di sebuah negeri Islam.
Tentang realitas Republik Islam:
Di negeri ini internet disensor. Semua link berbau pornografi akan otomatis dialihkan ke situs yang menyediakan informasi ajaran Islam. Namun pasca keributan seputar pemilu 2009, situs seperti facebook, twitter, youtube dan banyak lainnya juga diblokir.
Di jalan-jalan tidak ada baliho iklan dengan gambar wanita. Di televisi juga tidak ada film Hollywood ataupun konser dengan biduanita yang tidak menutup aurat.
Di jalanan, berlaku aturan berpakaian Islam. Bahkan wanita peserta conference dari Russia pun begitu masuk imigrasi di bandara sudah harus berpakaian tertutup. Minimal bercelana panjang, blazer dan kerudung menutup rambut dan leher. Kadang sedikit rambut depan masih terlihat, namun ini tak masalah dalam fiqih syiah, karena dianggap bagian wajah yang biasa terlihat. Namun ada juga yang menambah dengan chador, kerudung besar (setengah lingkaran dengan radius setinggi badan) warna hitam yang diselimutkan dari kepala dan menjuntai ke tanah. Agar tak lepas, chador ini harus selalu dipegang. Kalau wanita itu mencangklong tas, tas itu akan tertutup chadornya. Konon, hanya di kota suci Qom yang nyaris seluruh wanitanya memakai chador.

Di bus tempat penumpang wanita di depan, laki-laki di belakang. Untuk kereta ada gerbong khusus wanita. Transportasi umum di Iran sangat murah. Tiket bus 1000 Riyals (sekitarr Rp. 800) dan Metro hanya 2000 Riyals. Bensin hampir sama dengan di Indonesia, 4500 Riyals, tetapi ada quota. Setiap kendaraan dijatah sehari 2 liter, angkutan umum/usaha 10 liter. Di SPBU ada card-reader. Kalau jatah habis maka berlaku harga 7000 Riyals. GDP perkapita US$ 10.800, lebih dari 3x Indonesia.
Di Teheran tak ada jaringan toko atau restoran cepat saji internasional. Jadi jangan mencari KFC atau McDonald. Pepsi atau CocaCola saja amat terbatas, apalagi khamr. Mungkin ada satu dua di pasar gelap, tapi yang jelas tidak ada di toko resmi. Demikian juga Hotel seperti Hilton. Sejak embargo ekonomi pasca revolusi Islam, Iran bisa hidup tanpa simbol-simbol modernitas seperti itu. Banyak pengusaha Barat hengkang karena mengkhawatirkan perang atau pertumbuhan negatif. Apalagi, sejak revolusi Islam, terbit Undang-undang perbankan bebas riba. Walhasil, kartu kredit seperti Visa atau Mastercard juga tidak bisa dipakai. Namun pasar-pasar Iran tetap ramai. Satu jalan panjang penuh dengan penjual spareparts kendaraan. Di tempat lain penuh dengan penjual baju atau barang-barang hobby. Banyak merek yang hanya ada di Iran. Usaha Kecil dan Menengah booming. Konon perdagangan dengan negara yang netral terhadap politik Iran amat deras, misalnya dengan Jepang, Perancis atau China. Cash dibayar dengan devisa dari expor, terutama migas. Iran mungkin negara tanpa utang luar negeri.
Jalan-jalan di Teheran juga relatif bersih, memberi tempat yang cukup untuk pejalan kaki, pokoknya lebih nyaman dari Jakarta, walaupun masih jauh dari Singapura. Tetapi air PAM dapat langsung diminum. Di dekat masjid Imam Khomeini bahkan ada zona pejalan kaki yang sangat luas dan nyaman karena dinaungi pohon-pohon rindang.
Namun memang bagi turis pemburu hiburan, di Iran nyaris tak ada hiburan. Ini yang juga dikeluhkan generasi muda Iran yang lahir pasca revolusi tapi pernah keluar negeri. Mereka menginginkan kebebasan. Mereka belum pernah merasakan, bagaimana Iran sangat menderita di masa Syah Reza Pahlevi. Raja zalim itu ingin membuat Iran negara paling sekuler dan liberal, namun pada saat yang sama dia sangat koruptif dan menjalankan politik negara intel. Hingga awal 1979, jarang orang percaya bahwa Raja yang amat berkuasa itu dapat digulingkan oleh ulama sepuh yang telah diasingkan 15 tahun.
Tak ada setahun pasca jatuhnya Syah Iran, dilakukan referendum, dan 90% rakyat Iran setuju dengan sebuah konstitusi baru yang dibuat Ayatullah Khomeini. Dalam konstitusi itu, pemimpin tertinggi Iran (Imam) dipilih dari dan oleh Dewan Ulama (Wilayatul Faqih). Imam ini yang menjadi panglima tertinggi angkatan perang, mengangkat para hakim serta setengah anggota Dewan Penjaga Revolusi yang mirip Mahkamah Konstitusi. Sementara itu Presiden dipilih rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Parlemen membuat UU, namun dapat dicabut oleh Imam atas saran Dewan Penjaga Revolusi, bila dianggap bertentangan dengan Islam. Bila Presiden hanya berkuasa 4 tahun dan boleh dipilih sekali lagi, maka Imam mengabdi seumur hidup. Dalam ajaran syi’ah, masalah Imamat adalah bagian dari rukun iman. Dalam ajaran sunni, masalah kepemimpinan atau Khilafah adalah “min ma’luman bid dharurah”, tetapi bukan bagian rukun iman. Jadi kira-kira Imam adalah Khalifah, dan Presiden adalah Muawin Tafwidh, meski masih banyak bedanya.
Tetapi memang banyak kejutan dengan syi’ah ini. Begitu mendengar adzan, ada beberapa sisipan yang tidak lazim kita dengar, misalnya “Asyhadu an Ali Waliyullah! Asyhadu an Ali Hujatullah” dan “Hayya alal khoiru amal”. Di masjid jadi kikuk. Pernah orang KBRI sholat di masjid, karena mungkin “aneh” bagi orang sana, dia sampai difoto oleh intel masjid. Mungkin jaga-jaga, “ada penyusup sunni”.
Khutbah Jum’at juga lebih mirip orasi politik. Kadang ada yel-yel yang diteriakkan, “Hancurkan Amerika!”. Ini yang kadang ditakutkan oleh negeri-negeri Islam lainnya Maka undangan beasiswa ke Iran sering ditanggapi dingin oleh pemerintah kita. Namun demikian, dari Indonesia saja, kini ada 300 mahasiswa yang belajar agama di kota Qom. Apakah mereka akan dicuci otak dan jadi agen syiah di Indonesia? Atau mereka justru tertarik dengan wanita Iran yang menurut seorang mahasiswa yang terpental dari Qom (mungkin gagal dicuci otaknya): “memang cantik sekali, tapi kalau tidak matre , ya sangat syi’ah ” :-).
** ini re-published ** sepertinya pernah saya tulis di Notes, tapi koq tidak ketemu lagi ya ?
 Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.
Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.
Bekerja di
Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.
Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.
Bekerja di